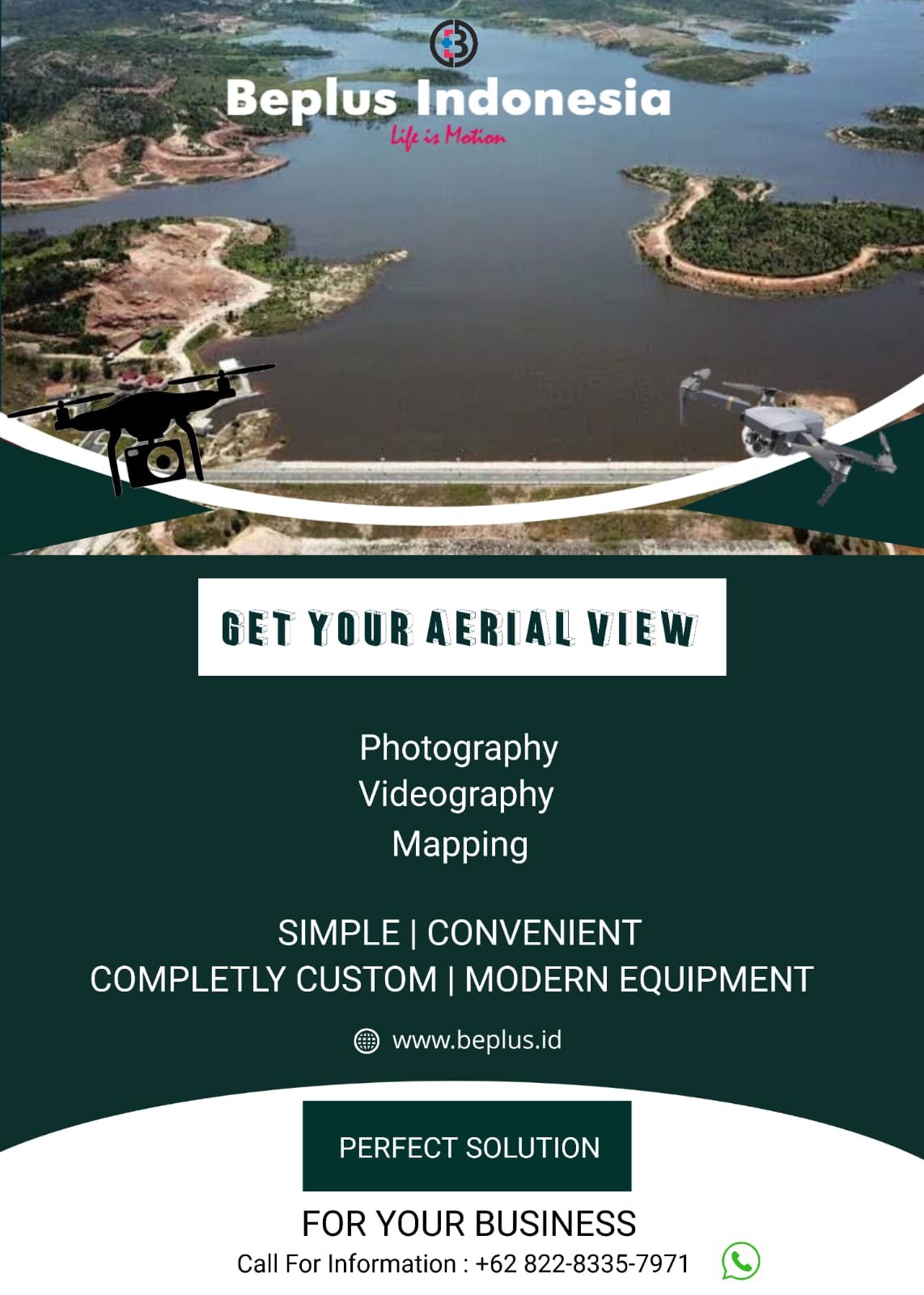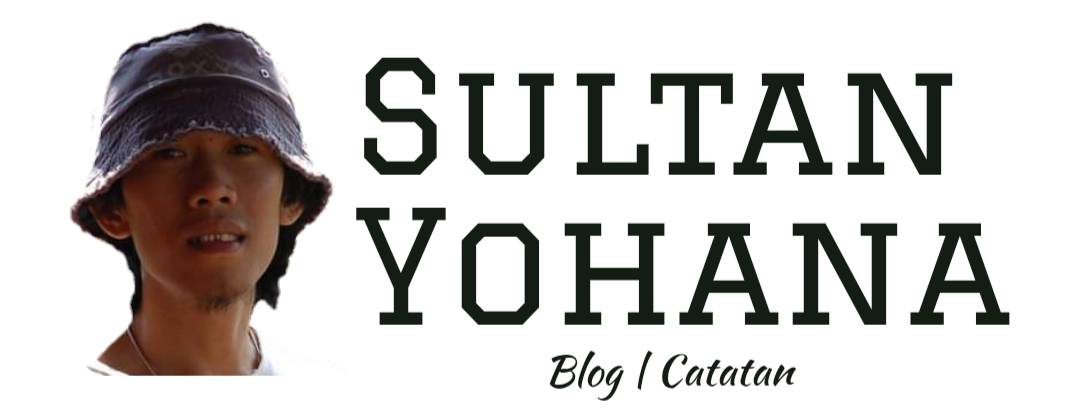Saya mencintai Gus Dur bukan karena bapak-ibu saya anggota fanatik Nahdlatul Ulama. Atau karena sejak kelas 4 madrasah saya dijejali pelajaran aswaja (ahlusunawaljamaah: ke-NU-an). Saya mencintainya karena penghargaannya yang luar biasa atas keanekaragaman. Bahwa manusia diciptakan tidak hanya berkulit legam seperti pria muda India yang saya saksikan itu, atau si cewek Tionghoa yang kulit mulusnya bak pualam itu. Dengan kerja kerasnya yang tak kenal lelah, Gus Dur mengusahakan keragaman itu menyatu di Indonesia. Sekian lama berjuang, justru saya menyaksikan sebuah praktik keanekaragaman yang begitu harmonis di Singapura. Negeri yang hanya berjarak 22 mil laut dari Batam. Saya yakin jika Gus Dur ada di samping saya ketika menyaksikan lenggang-kangkung sepasang sejoli di Harbour Front MRT tadi, dia akan menangis lirih. Sembari mendongengkan sebuah harapan tentang Indonesia yang benar-benar berbhineka.
Enam tahun wara-wiri di S’pore, terkadang saya bosan menyaksikan kesempurnaan negeri seluas 700-an kilometer persegi itu. Saya bosan menuliskan kesempurnaan di sana lewat rubrik “Rasa Singapura” di koran saya bekerja. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengakui, sebuah negara makmur dengan nasionalisme yang begitu menggelora, dibangung di atas keragaman. Di Spore: jika Anda orang India yang berdaya upaya, Anda akan berkesempatan menjadi orang luar biasa. Jika Anda Melayu yang mumpuni, Anda akan tampil memimpin. Jika Anda Tionghoa yang berdedikasi tinggi, Anda akan meraih kesuksesan. Dengan diskriminasi, negara hanya akan terjerumus pada permusuhan tak berkesudahan. Di Batam – Kepri – ini: me-Melayukan pegawai pemerintahan tentu bukan solusi, me-Tionghokan bidang usaha akan sangat berbahaya, membabukan Jawa tentu sangat menyakitkan.
Di Singapura, bibit kebencian etnis sekecil apa pun berusaha dienyahkan pemerintah. Tentara, polisi, pegawai pemerintah adalah siapa Anda yang warga negara Singapura, apa pun etnisnya. Di tempat-tempat umum, penanda ketertiban umum ditulis dengan aneka bahasa: Melayu-Inggris-India-Tionghoa. Iklan-iklan layanan masyarakat berusaha menampilkan dan mengikutsertakan semua lapisan etnis dan agama. Pemerintah selalu merangkul semua etnis rakyatnya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ada televisi dan koran khusus Tionghoa, tapi ada juga yang spesial untuk Melayu dan India.
Anda akan mudah menemukan wanita India lengkap dengan busana sarinya dan aneka ragam noda tanda ibadah di wajahnya. Di Bulan Hantu-nya Tionghoa, pemerintah tak akan berani mendenda orang-orang yang membakar aneka rupa barang sesembahan di jalan-jalan yang selalu menciptakan segunung sampah. Para Muslim/ah bebas mengenakan busana tertutup, bebas melaksanakan ibadah salat tanpa takut dianggap menkorupsi waktu. Dari semua itu, maka lahirlah generasi-generasi yang tak mempedulikan etnis dan hanya menghargai kemanusiaan. Keanekaragaman tentu tak bisa diseragamkan, keanekaragaman harus dilestarikan. Sebagaimana si pria India yang berpacaran dengan gadis Tionghoa yang saya temui di Stasion MRT Harbour Front akhir pekan lalu.
Tentu tidak sebiji sejoli itu saja yang kebetulan saya temui yang kemudian mendasari saya menyusunan artikel ini. Di mana-mana saya kerap menyaksikan orang Tionghoa – etnis yang dianggap paling tertutup di antara tiga etnis besar di Singapura – bisa bermesraan bahkan bercinta-cintaan dengan pasangan dari etnis-etnis yang lain. Kedai-kedai yang menjual masakan babi bisa berjualan berdampingan dengan warung masakan Muslim. Menyaksikan seorang Melayu yang menyodorkan uang sekedarnya bagi pengamen Tionghoa. Atau menyaksikan pesta-pesta yang dijejali tawa dan canda aneka bahasa.
Seandainya Gus Dur ada di samping saya. Mungkin dia akan sangat berduka, usahanya yang sedemikian keras untuk menyatukan keanekaragaman (bukan menyeragamkan), justru dengan sempurna bisa dilaksanakan di Singapura.
Sultanyohe@yahoo.com
Foto pinjam JPNN
Saya membayangkan Gus Dur ada di samping saya ketika melihat pemandangan ini: menyaksikan seorang pria muda etnis India yang kulit legamnya naudzubillah sedang jalan mesra dengan seorang gadis Tionghoa bertank-top krem yang sebagaian pundaknya terbuka gila. Kulit putih si gadis itu seperti pualam, mulus tanpa noda. Sesekali, tengan legam si India meraih pinggul si gadis: keduanya kemudian jalan lenggang kangkung bak macan lapar, memamerkan kemesraan, menunjukkan bahwa perbedaan bisa dipersatukan. Di Stasiun MRT Harbour Front akhir pekan lalu, sayangnya saya menyaksikan adegan itu seorang diri. Dengan segala sedih yang hingga kini masih tersisa, saya yakin Gus Dur kini tenang beristirahat di Jombang sana!
Saya mencintai Gus Dur bukan karena bapak-ibu saya anggota fanatik Nahdlatul Ulama. Atau karena sejak kelas 4 madrasah saya dijejali pelajaran aswaja (ahlusunawaljamaah: ke-NU-an). Saya mencintainya karena penghargaannya yang luar biasa atas keanekaragaman. Bahwa manusia diciptakan tidak hanya berkulit legam seperti pria muda India yang saya saksikan itu, atau si cewek Tionghoa yang kulit mulusnya bak pualam itu. Dengan kerja kerasnya yang tak kenal lelah, Gus Dur mengusahakan keragaman itu menyatu di Indonesia. Sekian lama berjuang, justru saya menyaksikan sebuah praktik keanekaragaman yang begitu harmonis di Singapura. Negeri yang hanya berjarak 22 mil laut dari Batam. Saya yakin jika Gus Dur ada di samping saya ketika menyaksikan lenggang-kangkung sepasang sejoli di Harbour Front MRT tadi, dia akan menangis lirih. Sembari mendongengkan sebuah harapan tentang Indonesia yang benar-benar berbhineka.
Enam tahun wara-wiri di S’pore, terkadang saya bosan menyaksikan kesempurnaan negeri seluas 700-an kilometer persegi itu. Saya bosan menuliskan kesempurnaan di sana lewat rubrik “Rasa Singapura” di koran saya bekerja. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengakui, sebuah negara makmur dengan nasionalisme yang begitu menggelora, dibangung di atas keragaman. Di Spore: jika Anda orang India yang berdaya upaya, Anda akan berkesempatan menjadi orang luar biasa. Jika Anda Melayu yang mumpuni, Anda akan tampil memimpin. Jika Anda Tionghoa yang berdedikasi tinggi, Anda akan meraih kesuksesan. Dengan diskriminasi, negara hanya akan terjerumus pada permusuhan tak berkesudahan. Di Batam – Kepri – ini: me-Melayukan pegawai pemerintahan tentu bukan solusi, me-Tionghokan bidang usaha akan sangat berbahaya, membabukan Jawa tentu sangat menyakitkan.
Di Singapura, bibit kebencian etnis sekecil apa pun berusaha dienyahkan pemerintah. Tentara, polisi, pegawai pemerintah adalah siapa Anda yang warga negara Singapura, apa pun etnisnya. Di tempat-tempat umum, penanda ketertiban umum ditulis dengan aneka bahasa: Melayu-Inggris-India-Tionghoa. Iklan-iklan layanan masyarakat berusaha menampilkan dan mengikutsertakan semua lapisan etnis dan agama. Pemerintah selalu merangkul semua etnis rakyatnya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ada televisi dan koran khusus Tionghoa, tapi ada juga yang spesial untuk Melayu dan India.
Anda akan mudah menemukan wanita India lengkap dengan busana sarinya dan aneka ragam noda tanda ibadah di wajahnya. Di Bulan Hantu-nya Tionghoa, pemerintah tak akan berani mendenda orang-orang yang membakar aneka rupa barang sesembahan di jalan-jalan yang selalu menciptakan segunung sampah. Para Muslim/ah bebas mengenakan busana tertutup, bebas melaksanakan ibadah salat tanpa takut dianggap menkorupsi waktu. Dari semua itu, maka lahirlah generasi-generasi yang tak mempedulikan etnis dan hanya menghargai kemanusiaan. Keanekaragaman tentu tak bisa diseragamkan, keanekaragaman harus dilestarikan. Sebagaimana si pria India yang berpacaran dengan gadis Tionghoa yang saya temui di Stasion MRT Harbour Front akhir pekan lalu.
Tentu tidak sebiji sejoli itu saja yang kebetulan saya temui yang kemudian mendasari saya menyusunan artikel ini. Di mana-mana saya kerap menyaksikan orang Tionghoa – etnis yang dianggap paling tertutup di antara tiga etnis besar di Singapura – bisa bermesraan bahkan bercinta-cintaan dengan pasangan dari etnis-etnis yang lain. Kedai-kedai yang menjual masakan babi bisa berjualan berdampingan dengan warung masakan Muslim. Menyaksikan seorang Melayu yang menyodorkan uang sekedarnya bagi pengamen Tionghoa. Atau menyaksikan pesta-pesta yang dijejali tawa dan canda aneka bahasa.
Seandainya Gus Dur ada di samping saya. Mungkin dia akan sangat berduka, usahanya yang sedemikian keras untuk menyatukan keanekaragaman (bukan menyeragamkan), justru dengan sempurna bisa dilaksanakan di Singapura.
Sultanyohe@yahoo.com
Foto pinjam JPNN