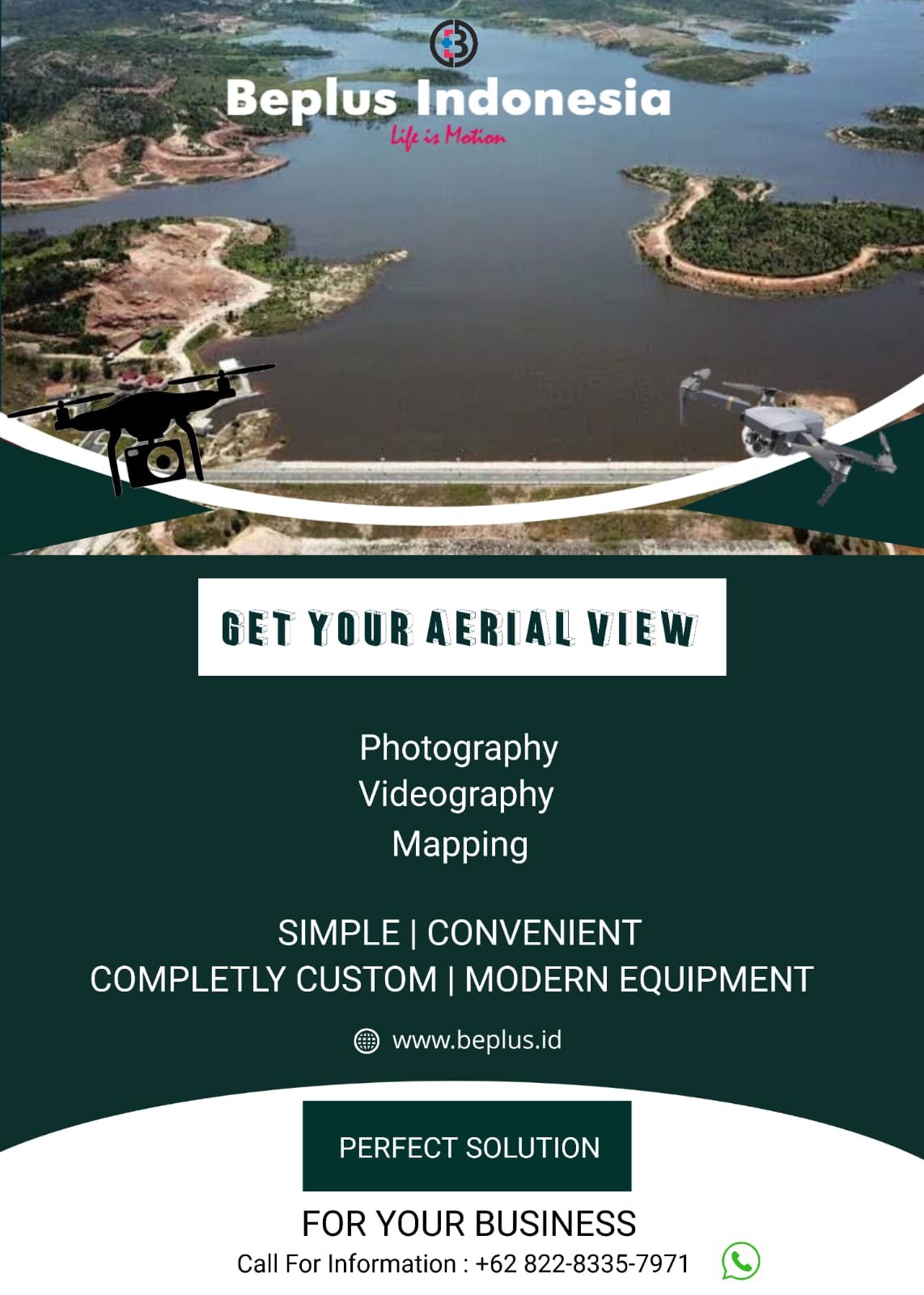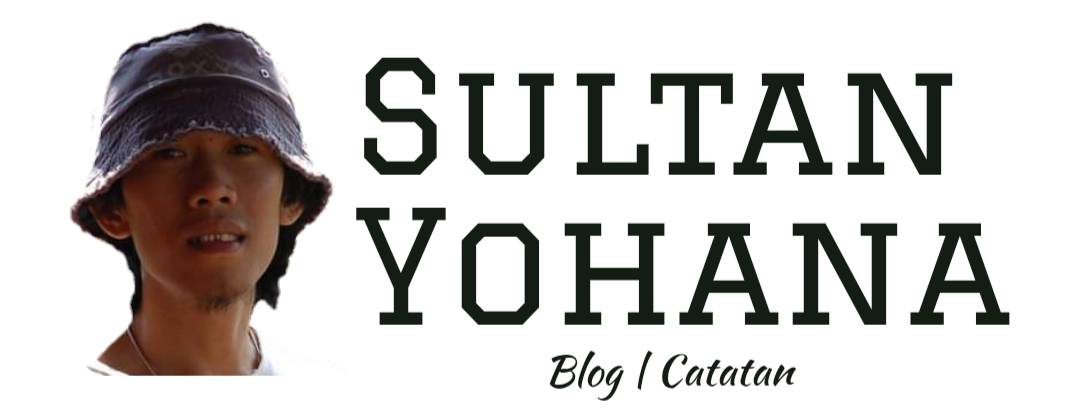Sialnya saya kalah. 18 finalis lomba penulisan itu, yang sedari 22 November diboyong ke Jakarta untuk presentasi tulisan masing-masing, hanya enam pemenang yang dipilih. Dan saya bukan salah satu dari enam itu.
Ketika puncak acara sekaligus penyerahan hadiah di auditorium II studio TVRI itu, saya hanya duduk tepekur di bangku penonton. Memandang nanar wajah-wajah sumringah rekan-rekan yang menang. Bubrah semua rencana yang telah saya susun sejak keberangkatan saya ke Jakarta. Saya tidak kecewa kalah. Saya kecewa karena rencana saya bubrah.
Soal sunat menyunat tadi, ini cerita dari seorang rekan guru di Batam. Saya juga guru (bahasa Indonesia di SMP Nurul Jadid, Bengkong). Juga wartawan. Tapi ketika dia hendak bercerita, dengan amat sangat rekan saya minta saya memposisikan diri sebagai guru. Sebagai sesama pengajar. “Tolong, jangan tulis di koranmu! Bisa-bisa sekolahku nggak dapat lagi bantuan dari Dinas (Pendidikan).” Dan saya, mengangguk menyetujuinya.
Beberapa waktu lalu di tahun 2007, sekolah tempat kawan saya mengajar, di Piayu, kebagian jatah bantuan Dinas Pendidikan Pusat. ”Besarnya lumayan. Kalau nggak salah sekitar seratus juta,” kata kawanku seraya menambahkan, “tapi itu di kuitansi.”
Diterima sekolah? “Ah tahu sendirilah! Angka-angka kuitansi sudah disiapkan dengan seksama. Berapa besarnya. Diperuntukkan untuk apa saja. Pokoknya rapi betul. Tapi ya itu, kami dibisiki sapa petugas Dinasnya, sepertiga dipotong ya!!!” begitu kira-kira jawaban rekan saya.
Kenapa harus saya kasih tanda seru tiga biji di akhir jawaban rekan saya? Ya, nada bicara si petugas – seperti ditirukan rekan saya – memang seolah sukarela minta keikhlasan dipotong. Tapi jika maca-macam, bisa-bisa dibuat sukar! He-he-he.
Sayang saya kalah. Kalau tidak, mungkin wajah saya akan nongol di televisi. Minta perhatian Pak Menteri Bambang untuk menegur anakbuahnya di Batam. Itu kalau disiarkan. Tapi saya yakin 100 persen. Seandainya saya menang, dan tetap berkoar, pasti bagian dari gambar saya dipotong orang-orang TVRI. Dan yang bisa menjadi saksi koaran saya cuma Pak Menteri dan 100-an guru teladan yang diundang dalam acara Hari Guru Nasional itu. pasti mereka kemudian bilang, “Ah, sunaat-menyunat itu mah…, sudah biasa Bos! Kayak kagak tau aja!”
Tapi tak apalah. Ini toh hanya sekedar asal cerita. Cerita menyambut Hari Guru Nasional 25 November lalu. Saya hanya berharap, semoga 25 November di tahun-tahun mendatang, tidak diperingati sebagai Hari “Sunat (menyunat)” Nasional. Semoga.
Andai saja saya menang dalam lomba penulisan feature tentang guru itu. Lomba gawean Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional. Andai saja saya yang maju ke panggungnya TVRI, 24 November lalu, untuk menerima hadiah dan bersalaman dengan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo. Andai saja saya diberi kesempatan beromong kosong, sepatah dua patah. Satu yang ingin saya sampaikan, “Pak Menteri, tolong dong anakbuah bapak di Dinas Pendidikan Batam jangan suka nyunat bantuan sekolah!”
Sialnya saya kalah. 18 finalis lomba penulisan itu, yang sedari 22 November diboyong ke Jakarta untuk presentasi tulisan masing-masing, hanya enam pemenang yang dipilih. Dan saya bukan salah satu dari enam itu.
Ketika puncak acara sekaligus penyerahan hadiah di auditorium II studio TVRI itu, saya hanya duduk tepekur di bangku penonton. Memandang nanar wajah-wajah sumringah rekan-rekan yang menang. Bubrah semua rencana yang telah saya susun sejak keberangkatan saya ke Jakarta. Saya tidak kecewa kalah. Saya kecewa karena rencana saya bubrah.
Soal sunat menyunat tadi, ini cerita dari seorang rekan guru di Batam. Saya juga guru (bahasa Indonesia di SMP Nurul Jadid, Bengkong). Juga wartawan. Tapi ketika dia hendak bercerita, dengan amat sangat rekan saya minta saya memposisikan diri sebagai guru. Sebagai sesama pengajar. “Tolong, jangan tulis di koranmu! Bisa-bisa sekolahku nggak dapat lagi bantuan dari Dinas (Pendidikan).” Dan saya, mengangguk menyetujuinya.
Beberapa waktu lalu di tahun 2007, sekolah tempat kawan saya mengajar, di Piayu, kebagian jatah bantuan Dinas Pendidikan Pusat. ”Besarnya lumayan. Kalau nggak salah sekitar seratus juta,” kata kawanku seraya menambahkan, “tapi itu di kuitansi.”
Diterima sekolah? “Ah tahu sendirilah! Angka-angka kuitansi sudah disiapkan dengan seksama. Berapa besarnya. Diperuntukkan untuk apa saja. Pokoknya rapi betul. Tapi ya itu, kami dibisiki sapa petugas Dinasnya, sepertiga dipotong ya!!!” begitu kira-kira jawaban rekan saya.
Kenapa harus saya kasih tanda seru tiga biji di akhir jawaban rekan saya? Ya, nada bicara si petugas – seperti ditirukan rekan saya – memang seolah sukarela minta keikhlasan dipotong. Tapi jika maca-macam, bisa-bisa dibuat sukar! He-he-he.
Sayang saya kalah. Kalau tidak, mungkin wajah saya akan nongol di televisi. Minta perhatian Pak Menteri Bambang untuk menegur anakbuahnya di Batam. Itu kalau disiarkan. Tapi saya yakin 100 persen. Seandainya saya menang, dan tetap berkoar, pasti bagian dari gambar saya dipotong orang-orang TVRI. Dan yang bisa menjadi saksi koaran saya cuma Pak Menteri dan 100-an guru teladan yang diundang dalam acara Hari Guru Nasional itu. pasti mereka kemudian bilang, “Ah, sunaat-menyunat itu mah…, sudah biasa Bos! Kayak kagak tau aja!”
Tapi tak apalah. Ini toh hanya sekedar asal cerita. Cerita menyambut Hari Guru Nasional 25 November lalu. Saya hanya berharap, semoga 25 November di tahun-tahun mendatang, tidak diperingati sebagai Hari “Sunat (menyunat)” Nasional. Semoga.