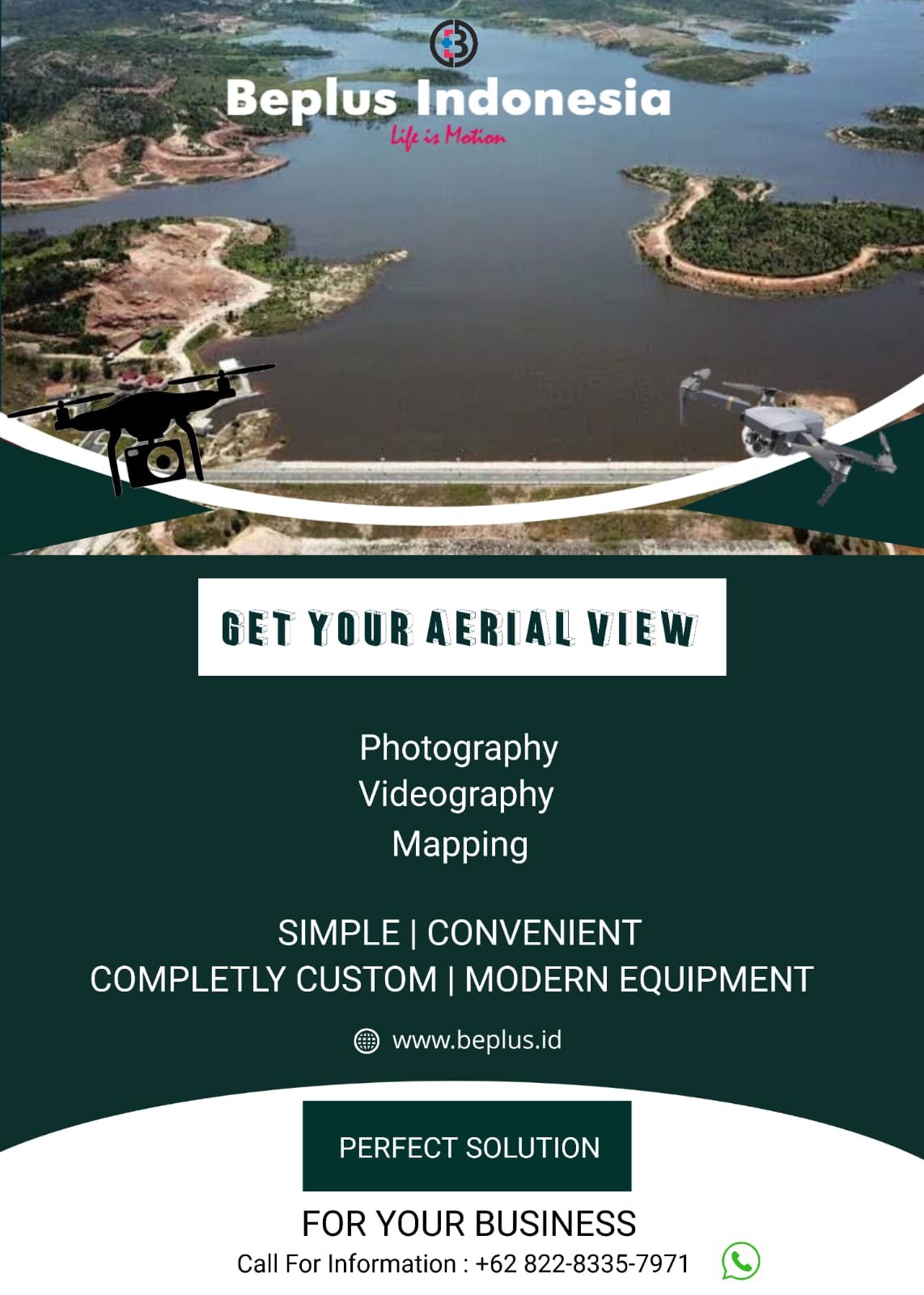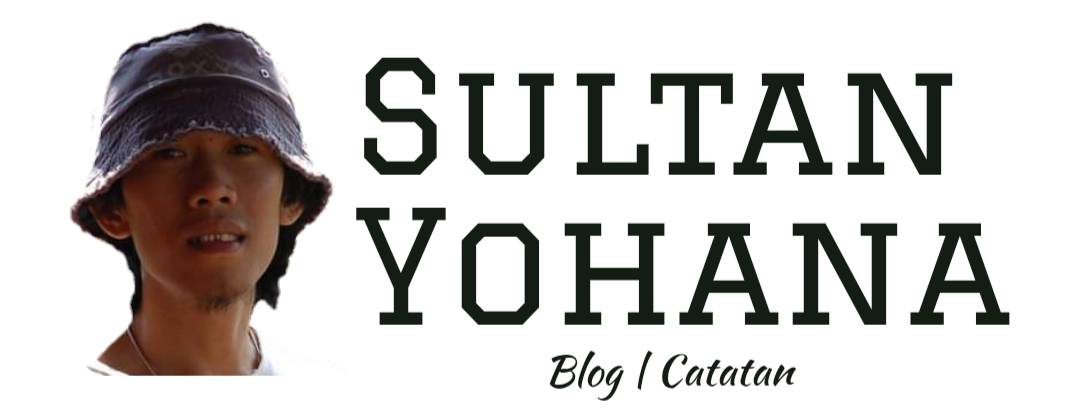: Santri, yang dicintai dan dibenci.
“Buk, aku pingin mondok.”
“Yo apik iku le, aku yo kepingin mondokno awakmu.”
“Tapi,” tambah ibu lagi, “duite sopo sing digawe ngirim lek awakmu mondok?”
Saya teringat obrolan itu, terjadi kira-kira ketika saya SMP kelas tiga. Untuk kali ke sekian, saya mengutarakan keinginan untuk mondok, menjadi santri. Tapi, lagi-lagi ibu berkilah soal ketidakmampuannya memondokkan saya. Ketika itu, keuangan ibu benar-benar sangat memprihatinkan. Jika sudah terbentur urusan ini, saya tidak bisa apa-apa lagi.
Di kampung halaman saya, Singosari, Malang, Jawa Timur; nyantri adalah kebiasaan yang lumrah. Bocah-bocah selulus SD atau SMP, biasa dipondokkan. Tidak ada yang istimewa. Bahkan Kecamatan Singosari sendiri, terkenal sebagai “kota santri”. Ada banyak pondok pesantren, besar maupun kecil di kecamatan kami. Bahkan di kelurahan tempat tinggal saya, tercatat ada delapan pondok pesantren yang cukup punya nama. Belum lagi ditambah yang kecil-kecil. Saban tahun, ribuan santri datang ke Kecamatan Singosari. Beberapa di antaranya bahkan ada yang dari luar negeri.
Mau tak mau, kehidupan warga Singosari begitu terpengaruh dengan kehidupan pesantren. Banyak bisnis tercipta karena kedatangan santri ini. Namun juga banyak “sampah” yang dihasilkan mereka. Banyak masalah timbul karena kebanyakan santri yang datang dari latar-belakang dan budaya berbeda dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat, terutama pemuda-pemuda yang seusia santri, tak jarang memusuhi, namun juga menyayangi (baca: membutuhkan) para santri.
Di aktifitas sehari-hari pun demikian. Di lapangan bola, kami seringkali harus berbagi tempat untuk bermain. Di belik pemandian umum juga. Di sekolah-sekolah di seantero Singosari hampir semuanya punya siswa yang berstatus santri. Bahkan di warung kopi, di persewaan ding-dong (kini mungkin Playstation), warung lesehan, pasar, masjid; semuanya harus berebut antri dengan para santri. Kanan-kiri-depan-belakang, di sekeliling saya semuanya adalah santri.
Nyantri memang bukan urusan ngaji atau menuntut ilmu saja! Yang datang untuk nyantri bukan semua mereka yang benar-benar serius ingin pintar. Banyak di antara mereka yang nyantri karena terpaksa. Banyak santri yang dipondokkan karena orangtua mereka tak mampu mengendalikan kebandelan mereka. Banyak santri nakal, banyak santri goblog, juga banyak santri yang ndak niat ngaji.
Dan yang demikian, terkadang menciptakan kejadian-kejadian konyol nan menggelikan. Di Kali (sungai) Kembang misalnya, saya seringkali memergoki para santri, dari balik semak-semak ngintip perempuan-perempuan mandi. Saya memergokinya berkali-kali, karena kebetulan saya juga punya kebiasaan mandi di kali. Masyarakat setempat memang biasa mandi di kali. Jika sudah begini, saya biasanya akan diam-diam, ngageti mereka, atau melempar sesuatu di dekat mereka. Gedebuk…, larilah mereka lintang pikung, bahkan tak jarang sampai terjatuh-jatuh.
Saya juga mengetahui banyak santri yang suka minum-minuman keras, atau suka berantem. Bahkan saya punya karib, seorang santri asal Sidoarjo, yang sepertinya mondok hanya untuk mencari ilmu kanuragan saja. Banyak jimatnya, dan banyak pula masalahnya. Seringkali dia diusir pondok setelah buat ulah yang tak “termaafkan”, seperti berkelahi. Lucunya, jika diusir, dia cuma pindah dari pondok A ke B yang jaraknya cuma sepelemparan batu. Saat pindah karena terusir, biasanya dia datang ke rumah: menitipkan bermacam-macam jimat pada saya. Dan satu pesan yang selalu dikatakan ketika nitip jimat-jimatnya; “Awas, ojo sampek digowo nang jeding!” Awas, jangan sampai (jimatnya) dibawa masuk kamar mandi.
Meski sangat bandel dan punya banyak musuh, santri kawan saya itu sangat baik pada saya. Suka melindungi saya. Suka mentraktir saya. Maklum saja, setiap kali ulangan sekolah, dia biasa nyontek ke saya.
Rata-rata, santri yang datang berasal dari kota yang lebih besar dari Singosari, atau yang latar-belakang keluarga berekonomi cukup mampu. Setidaknya cukup kaya untuk rata-rata masyarakat Singosari seperti keluarga saya. Banyak di antara mereka yang statusnya anak juragan tambak, juragan kain, punya toko emas, tuan tanah, dls. Ini bisa dimaklumi. Biaya mondok tidak murah, bahkan sangat mahal jika mengukurnya dari – misalnya – ukuran keluarga saya.
Apalagi jaman sekarang. Biaya mondok tambah gila-gilaan. Susah sekali mencari pesantren yang mau “dibayar” dengan mbabu, sebagaimana ibu saya dulu mondok sekaligus jadi buruh. Nyaris semua pondok sekarang “dimodernisasi”. Yang artinya, apa-apa serba duit! Juli 2017 lalu, saya tanya pada kakak yang baru mondokin anak gadisnya. Piro Neng biaya masuk’e Astina (nama ponakan saya tercinta)? Jiangkrik…, jawabannya membuat saya nyaris “pingsan”.
Dengan kemampuan finansial mereka, para santri-santri itu kerap membuat warga sekitar “iri hati”. Banyak warung makan mereka kuasai, serta pamer aneka barang-barang bagus juga seringkali “menyakiti” hati masyarakat setempat yang kurang mampu. Meski, tentu saja banyak juga santri yang minim kiriman uang, dan biasa menyiasati makan dengan ngliwet sendiri di pinggir kali. Kehidupan mandiri dan bebas inilah yang membuat saya pribadi ingin menjadi santri.
Banyak santri-santri yang datang di kecamatan kami juga bocah-bocah manja yang sebetulnya belum cukup mampu mengurus diri sendiri. Ditambah fasilitas dan infrastruktur pondok yang belum memadai, kehidupan mereka kemudian terjerembab dalam banyak masalah di kehidupan praktis. Banyak santri otaknya tak cukup mampu, akhirnya lebih banyak nongkrong di persewaan Playstation ketimbang majelis pengajian. Mereka juga banyak yang kotor dan pemalas, hingga para santri itu terkenal punya banyak penyakit kulit. Penyakit gudig dan sebangsanya. Jika santri-santri itu kebetulan mandi di belik umum, sudah bisa dipastikan warga sekitar akan memilih tidak mandi terlebih dulu sebelum airnya berganti. Takut tertular gudig yang biasa diidap para santri.
Oh ya, gudig adalah sejenis penyakit kulit yang biasa menyerang sela-sela jemari tangan maupun kaki, gatal disertai bentol-bentol bernanah, serta mudah sekali menular.
Dengan kemampuan uang mereka juga, banyak santri lelaki yang sangat “dominan” dalam merebut perhatian cewek-cewek cantik warga setempat. Ini jelas menjengkelkan para pemuda di sana, apalagi yang cuma bermodal “sandal jepit”. Jika ada seorang santri anak juragan tambak Sidoarjo “naksir” cewek setempat, misalnya, hmmmm…., sudah “habislah” harapan pemuda setempat untuk menarik hati si cewek. Bisa dipastikan, 90 persen peluang si cewek disunting si santri akan jadian. Bakal berlanjut ke pelaminan.
Orangtua mana yang tak gembira punya besan juragan tambak yang kaya raya? Beberapa sepupu jauh saya, menjadi “korban” dipersunting santri-santri anak orang kaya. Hehehe…
Tapi bagaimanapun penuh masalahnya para santri-santri itu, warga sekitar Singosari secara umum justru menyambut keberadaan mereka dengan baik, dengan tangan terbuka. Sepanjang ingatan saya, belum pernah ada insiden-insiden besar yang melibatkan santri dengan warga hanya gara-gara masalah di atas. Warga tetap menghormati keberadaan para santri. Dan rasa hormat itu, tentu saja karena kyai-kyai pengasuh pesantren tersebut adalah panutan kami, guru bagi warga sekitar.
Saya sendiri, masih percaya, mondok menjadi salah satu cara yang baik menuntut ilmu, sembari memandirikan generasi muda. Dengan catatan, harus benar-benar jeli melihat siapa kyai pengasuhnya. Karena di jaman yang penuh godaan uang ini, siapa pun bisa pura-pura jadi kyai. Agar punya pondok pesantren yang bisa dijadikan “sapi perahan”.
Ayo nyantri!
Foto: jalan protokol yang membelah Kecamatan Singosari.