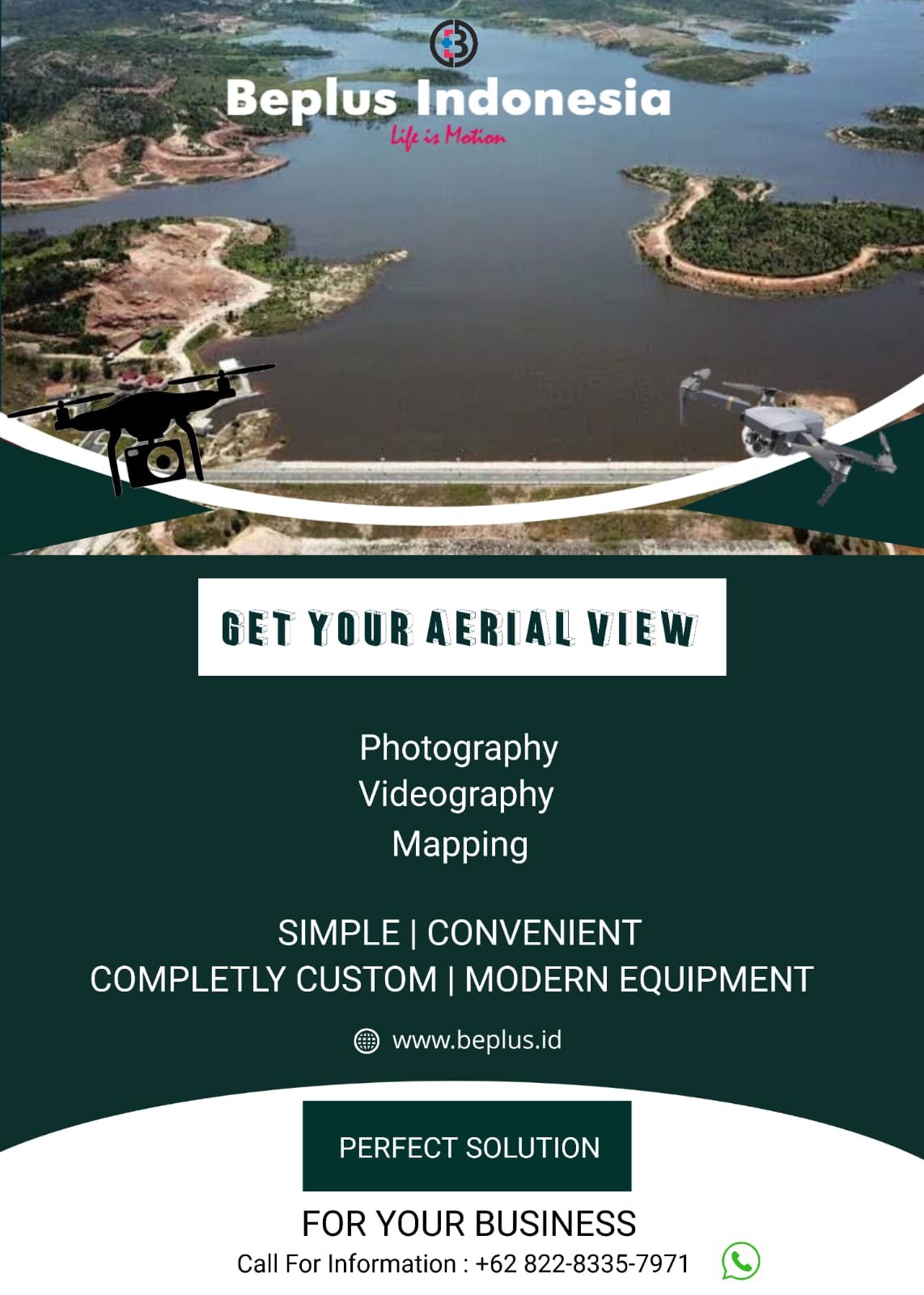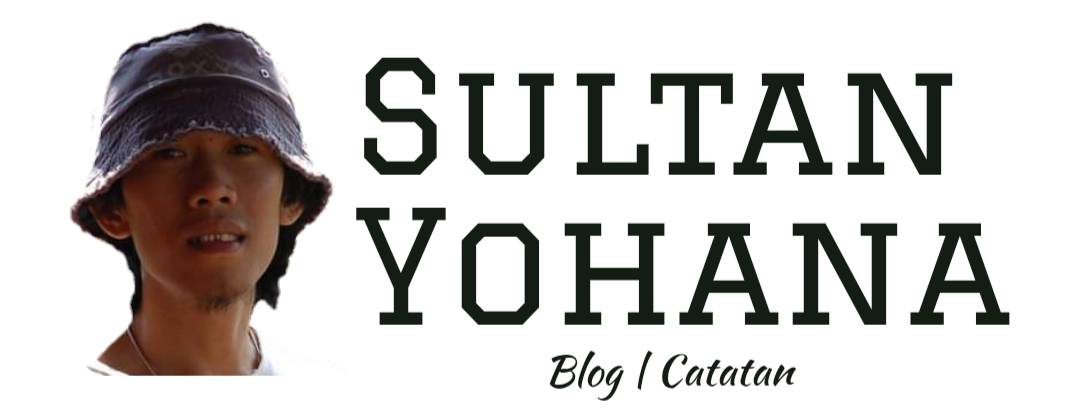: Ayo kembali menjadi manusia lagi.
(Tulisan ini sudah sejak Desember 2015 saya susun, tapi lupa saya upload, dan baru teringat ketika ramai-ramai angkutan di Malang mogok)
Saya masih ingat betul obrolan dua sopir mikrolet (angkutan umum), Juni 2015 silam. Obrolan antara sopir mikrolet jurusan Karangploso-Arjosari (KA) yang mobilnya kami tumpangi; dengan rekannya, sopir jurusan Lawang-Arjosari (LA). Kedua kendaraan, ketika obrolan terjadi, saling berdampingan di kemacetan parah di depan Pabrik Rokok Bentoel, Malang. Warga aseli Malang pasti sangat tahu lokasi ini.
“Tekan terminal oleh mung iki tok, ora nambah blas,” kata si sopir KA sembari melongokkan kepalanya ke luar jendela, menghadap rekannya. Di dalam mobil, memang cuma ada saya sekeluarga; berempat plus ponakan saya, Astina, yang naik dari Terminal Arjosari. Tidak ada penumpang lainnya. Setali tiga uang, saya lihat mikrolet LA cuma ada satu penumpang, ibu-ibu paruh baya yang tengah duduk di bangku panjang belakang sopir, yang entah melamun memikirkan apa ketika saya perhatikan.
Si sopir LA tertawa getir. Saya hampir tertawa, ketika melihat giginya yang nyaris ompong, meski usianya tak terlalu tua, kira-kira 45an tahun. Pertanda gigi tak dirawat baik. “Indonesia sekali,” bathin saya.
“Iki mulai tekan lor mbalik ngalor meneh mung ngebut tok, ora mandeg blas,” balas si sopir ompong. Maksudnya, sejak berangkat dari utara (Lawang) hingga sampai Terminal Arjosari dan kembali ke Lawang, lagi, mikrolet yang disopirinya jalan terus tanpa pernah berhenti untuk menaikkan penumpang. Ironis, untuk sebuah angkutan di kota Malang yang pernah menjadi sangat populer dan menjadi “jalur mahal” karena ramainya penumpang.
Saya, sejak SMA (SMP kadang-kadang naik, tapi lebih sering jalan kaki/bersepeda) hingga kuliah, selalu memanfaatkan mikrolet jurusan LA untuk pergi dan pulang sekolah/kuliah. Rumah saya di Singosari, dan ketika SMA saya sekolah di Lawang, di bagian utara Malang. Pulang pergi sekolah selalu menumpang mikrolet jurusan LA.
Saat kuliah di Universitas Negeri Malang, yang berada di pusat kota, selain menumpang LA untuk membawa saya dari Singosari ke Terminal Arjosari (juga sebaliknya), saya harus lanjut dengan menumpang mikrolet ADL (Arjosari-Dinoyo-Landungsari) atau AL (Arjosari-Landungsari). Kedua mikrolet ini, jalurnya melewati kampus saya.
Masyarakat Malang sepantaran saya, antara 35 hingga 50 tahun, pasti tahu betapa melegendanya Mikrolet jurusan LA pada dekade 90-an hingga awal-awal pergantian milenium. Saban pagi, susahnya setengah mati bisa menumpang mikrolet ini. Saban pagi penumpang penuh berdesak-desakan, saya kerap duduk di bangku kernet, karena saking sesaknya. Siang hingga malam, mikrolet jurusan ini tak pernah sepi. Para sopir LA makmur-makmur karena pendapatan mereka cukup, belum lagi pemilik mikroletnya. Kendarannya juga bagus-bagus, terawat, dan kadang berhias; menandakan pemilik mikrolet punya cukup uang untuk merawat.
Tapi sekarang, seperti obrolan di atas tadi, keluhan si sopir ompong tadi memberi gambaran, betapa susahnya mencari penumpang. Mikrolet-mikrolet pun kondisinya begitu memprihatinkan. Sana-sini karatan, suara kriek… kriek…., terdengar saat kita menumpang, dan benar-benar tidak nyaman. Saya yakin, karena sepi penumpang, pemilik mikrolet tidak punya budget untuk memberi perawatan kendaraannya. Sudah bertahan hidup pun, mereka bersyukur.
Siang menjelang sore itu, macet di daerah Karanglo begitu parah. Padahal jam belum menunjukkan jam kerja usai. Masih jam 4-an lebih dikit. Sepanjang saya melihat, kanan-kiri-depan-belakang, mobil pribadi mendominasi jalan yang lebarnya tak pernah berubah sejak saya kecil itu. Bagus-bagus mobilnya. Juga motor yang kebanyakan masih kinyis-kinyis. Motor-motor gaek semacam Honda GL-100, Astra-800, atau Astrea Prima, dan sebangsanya, sepertinya sudah “habis” ditelan jaman. Padahal di negeri seperti Malaysia, dealer-dealer motor pun masih menjual Astrea Prima baru.
Saya membathin, warga di kota saya, juga kota-kota di Jawa Timur, sudah pada makmur semua. Bisa beli kendaraan baru semua, hingga nyaris tidak ada ruang tersisa di jalan raya, juga bagi mikrolet-mikrolet yang kian menua, lapuk, ditinggalkan, dan pada akhirnya – mungkin – akan sekarat dan mati dengan perlahan. Mikrolet yang saya tumpangi baru mendapat penumpang lain, setelah masuk wilayah Karangploso. Kebanyakan yang menumpang pun orang-orang tua, atau bapak maupun ibu-ibu yang dari tampangnya, memang ndak bisa naik motor.
***
Saya bertemu Syam, seorang Indonesianis yang bekerja di Singapura, beberapa waktu lalu, di Stasiun MRT Ang Mo Kio. Dia membeli lensa dari saya. Sebagai sesama Indonesia, ngobrol lama pun tak terelakkan. Mulai dari obrolan seputar hobi kami; fotografi, hingga thethekbengek seputar dinamika Indonesia dan Singapura. Syam mengaku hampir lima tahun tinggal di Singapura. Pekerjaannya lumayan sip: ia adalah peneliti di sebuah perusahaan tambang yang berkantor di Singapura. Gajinya tentu saja gedhe, apalagi jika dibandingkan bapak rumahtangga seperti saya yang nyambi jual beli barang bekas.
Selama di Singapura, Syam bercerita, dia seorang diri. Istri dan seorang anaknya yang masih balita ditinggal di Yogyakarta, tempat dia bermukim di Indonesia. Saban sebulan sekali, dia balik Yogya. Memang, tiket pesawat murah yang saat ini mudah didapat, sangat membantu orang-orang seperti Syam. Ketika saya tanya, kenapa tak bawa anak-istrinya ke Singapura, toh dia dapat jatah flat (apartemen) dari perusahaan tempatnya bekerja?
“Kasihan, ndak tega. Ndak punya mobil. Repot banget. Masak sama balita harus naik turun bus atau MRT,” begitu jawabannya. “Mau beli mobil di sini, lihat harganya miliaran gitu, ndak tega sama duitnya.”
‘Jangkrik,’ bathin saya. Jawaban Syam itu, sedikit “melukai” hati saya yang hampir sepuluh tahun terakhir ini “naik-turun” bus atau kereta bersama anak-anak saya. Bahkan tiap tahun, saya kerap oyong-oyong mereka liburan di tempat-tempat cukup panjang perjalanannya. Entah saya yang memang terbiasa kerja kasar ataukah Syam yang sedikit manja, selama itu pula saya tak merasa kasihan sama anak-anak saya. Tak merasa repot. Bahkan, sejauh ini, saya enjoy banget memanfaatkan angkutan umum di Singapura yang nyaman, ber-AC, harga terjangkau, serta aman itu. Saya selalu menikmati angkutan umum di Singapura. Terkadang, saat lama pulang ke Indonesia, yang saya rindukan dari Singapura adalah tertib dan nyamannya naik kendaraan umum.
Di Batam saya sempat punya mobil selama sekitar tiga tahun, sebelum akhirnya saya jual karena saya pindah ke Singapura. Memang, nikmat memiliki kendaraan roda empat, tapi itu tidak serta merta membuat saya kehilangan kebiasaan menumpang kendaraan umum. Macet dan susahnya cari parkir di Batam, terkadang menjadi hal yang sangat menjengkelkan. Tak jarang saya malah meninggalkan mobil di satu tempat, dan saya pergi dengan menumpang metrotrans (sebutan mikrolet di Batam), busway, atau ojek. Salah satu alasan saya melakukan ini, JUGA UNTUK melawan rasa NYAMAN yang ditawarkan mobil pribadi.
Dalam keluarga pun, menumpang angkutan umum sudah menjadi ritual kami setiap kali pergi ke satu kota. Di mana saja kami datang, ritual tersebut kami lakukan. Khusus bagi saya, hal itu memberi pengayaan cara pandang berbeda atas segala perkembangan di kota yang sedang saya kunjungi. Saya menikmati berinteraksi dengan banyak penumpang, banyak orang asing. Belajar dan mempelajari karakter banyak orang. Terkadang menemukan hal unik-unik dari mereka. Banyak pelajaran juga bisa dipetik untuk anak-anak saya saat menumpang angkutan umum. Pelajaran berbagi, pelajaran antri, atau bahkan pelajaran memberi pertolongan pada hal-hal sederhana, atau sekedar mengucap terimakasih kepada sopir yang telah bersusah-payah mengantarkan kita dengan selamat.
***
Saya percaya terhadap teori, ‘bahwa pembangunan dan kualitas sebuah kota, bisa dilihat dari bagaimana keadaan jalan rayanya’. Jalanan yang amburadul, macet, rusak sana-sini, lampu penerangan tidak baik; pedestrian yang buruk, bahkan tidak ada, atau rambu-rambu yang kerap dipatahkan, menunjukkan pula bagaimana rusaknya masyarakat kota itu. Khusus untuk macet, bukan hanya soal banyaknya kendaraan dan lambatnya perkembangan jalan raya saja yang menjadi penyebab utamanya. Di kota-kota di Indonesia, saya justru melihat, kondisi macet lebih banyak DISUMBANGKAN oleh gaya hidup dan keserakahan mereka.
Saat saya masih SMA, antara tahun 1994 hingga 1997, butuh tak lebih dari 30 menit untuk sampai ke sekolah. Setelah kira-kira jalan kaki selama 15 menit untuk 1,5 kilometer jarak dari rumah ke jalan raya, saya kemudian menumpang mikrolet jurusan LA. Angkot hanya butuh tak lebih dari 10 menit untuk sampai di dekat sekolah yang jaraknya sekitar tujuh kilometer. Itupun masih kerap berhenti-untuk menaik-turunkan penumpang. Sekarang, bulan Juni 2015 lalu, nyaris satu setengah jam perjalanan dengan mobil sewaan dari rumah kakak saya di Ngijo, Karangploso, menuju Lawang, yang jaraknya tak lebih dari 20 kilometer.
Di mana-mana macet parah. Bahkan untuk belok kendaraan pun, susahnya setengah edan. Setiap orang, setiap keluarga, sepertinya berlomba-lomba punya kendaraan sendiri. Motor mungkin sudah menjadi barang “ecek-ecek” saja. Masyarakat bahkan banyak yang punya lebih dari satu mobil. Satu mobil untuk bapak, satu untuk ibu, satu untuk anak, dan satu motor untuk anak yang lain. Lha, bagaimana tidak macet, kalau jalanan sejak jaman saya bayi sampai sekarang tak nambah-nambah, kendaraannya yang tiap hari tambah.
Gaya hidup berkendara pribadi ini, jelas membuat bisnis angkutan umum koit. Bisnis sepi, berimbas juga pada ketidakmampuan mereka mengupgrade kendaraan atau kenyamanan/keamanan kendaraan mereka. Belum lagi pemerintah yang begitu memberi kebebasan dan kemudahan memilik kendaraan, serta gampangnya memberi izin untuk usaha-usaha yang lebih membuat pelaku bisnis angkutan umum lama kian sekarat. Dan kini, DERITA sopir mikrolet ditambah oleh keserakahan masyarakat bermobil yang memanfaatkan mobil-mobil mereka sebagai angkutan berbasis online, Grab atau Uber. Sungguh serakahnya, orang-orang yang sebetulnya berkecukupan, dan punya kerja baik itu. Padahal mungkin, ketika mereka bersekolah, sopir-sopir mikrolet yang membawa mereka ke sekolah, berjasa begitu besar pada mereka.
Kita semua berdosa dengan kondisi ini, dan satu-satunya penebusan dosa adalah, sebanyak mungkin mengurangi “keserakahan nafsu” untuk memiliki dan memakai kendaraan pribadi. Kembali membiasakan diri memakai kendaraan umum. Kembali membiasakan jalan kaki. Kembali membiasakan menyapa sana-sini, bertemu muka langsung banyak orang. Untuk kembali menjadi MANUSIA lagi. Bukan zombie yang tidak peduli kanan-kiri.
Naik kendaraan pribadi itu seperti bersosialisasi di media sosial maya, dengan segala macam keterbatasan dan efek negatifnya. Tentu sama sekali tidak sama ketika kita langsung bertemu dan bertatap muka dengan banyak orang, atau nongkrong bertatap-muka langsung dengan manusia.
Jadi, ketimbang mengeluhkan macet di mana-mana, mendingan letakkan kendaraan pribadi, dan ayo naik angkutan umum. Agar bapak bergigi ompong sopir LA tadi, kembali sumringah senyumnya.
Ayolah…, buang jauh-jauh gengsi Anda!