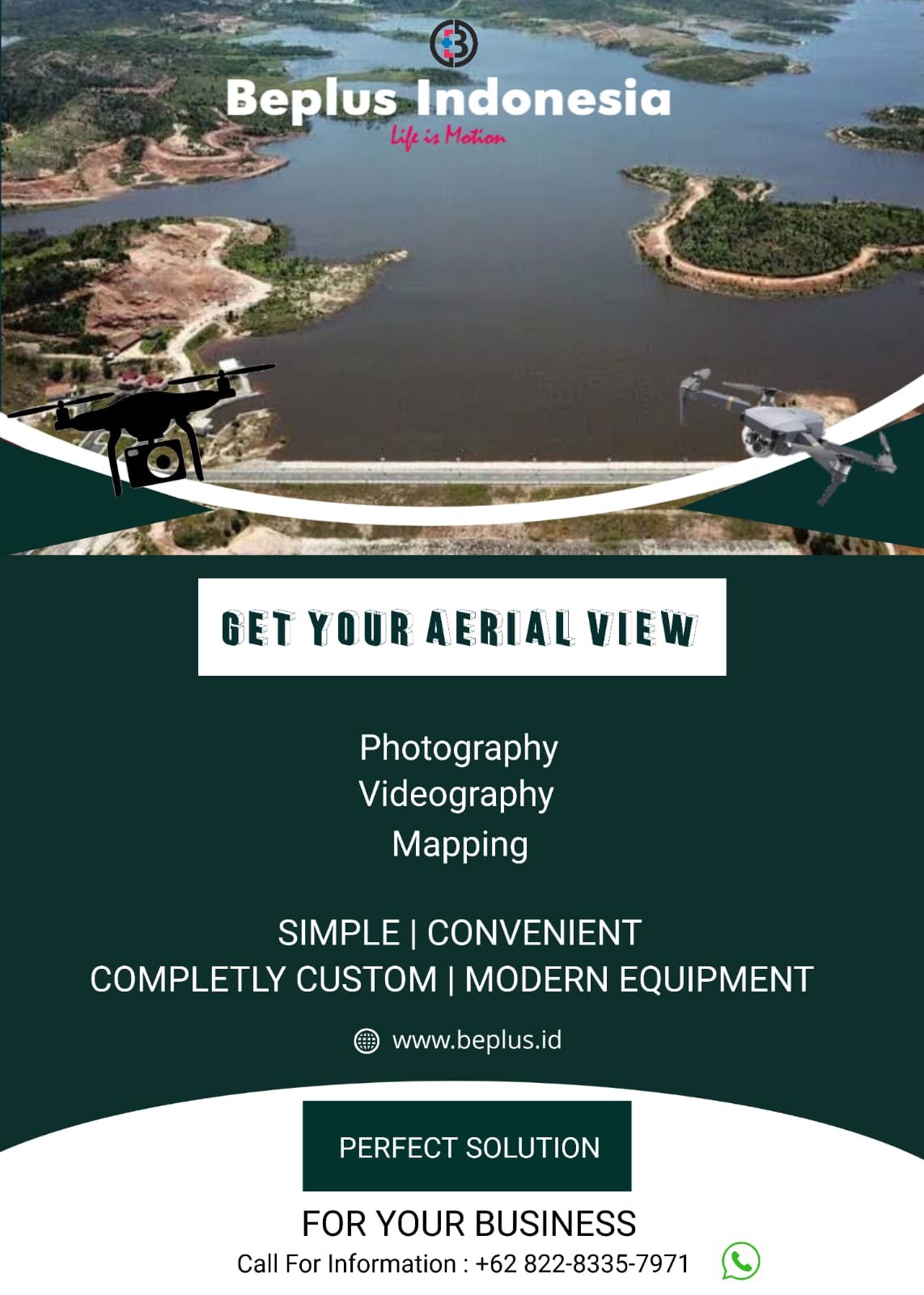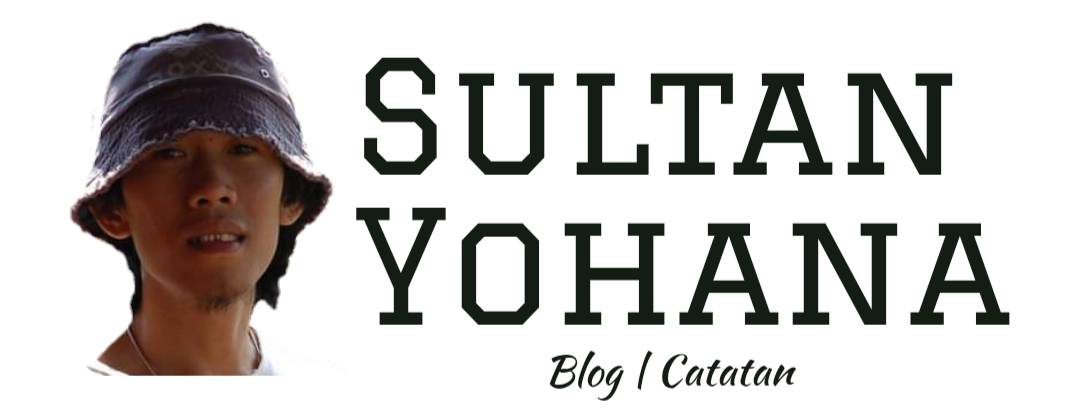Duduk di sofa sembari matanya tak mau lepas dari layar i-Pad yang digenggamnya, Ken, anak sulung kami, memanggil saya. Dalam bahasa Inggris, dia minta saya untuk duduk di sampingnya. Menemaninya bermain game di i-Pad kesayangannya itu. Tugas rutin tiap kali saya pulang ke Singapura.
“Pakai bahasa Indonesia!” perintah saya sembari duduk di sampingnya. Saya mengatakan itu juga dengan bahasa Indonesia. Sebagai mantan guru Bahasa Indonesia – serta bapaknya – saya berkewajiban membuat anak saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dia sebetulnya cukup mengerti setiap kata dari bahasa Indonesia yang saya ucapkan. Sehari-hari, saya dan istri saya memang berbicara dengan bahasa Indonesia. “Bukankah darah kamu setengah darah Indonesia?” kata saya lagi.
“Tapi saya orang Singapura. Saya cinta Singapura,” jawab Ken, masih dengan bahasa Inggris yang jauh lebih baik dari yang saya kuasai. “Singapura bersih. Nice. Indonesia kotor, kawan-kawan (di Indonesia) kalau buang sampah sembarangan,” kata Ken lagi, mengemukakan alasan kenapa dia cinta Singapura.
Saya terperanjat dengan jawaban anak saya itu. Saya tak pernah mengajari jawaban-jawaban di atas. Sungguh. Jawaban yang keluar dari bocah berusia 6 tahun seperti dia, membuat saya berpikir; apakah bocah sekecil ini sudah bisa mempelajari sekelilingnya. Dan saya menjawab sendiri, “ya, tentu saja bisa”.
Di Singapura, selain memang diajarkan hal-hal praktis – namun sangat penting – seperti tertib antri atau membuang sampah di tempatnya; pada praktiknya hal-hal semacam itu sudah terpraktikkan di depan mata mereka. Orangtua di negeri yang sudah maju seperti Singapura, mereka jauh lebih khawatir anak mereka tak bisa tertib antri ketimbang tak bisa menguasai pelajaran matematika.
Sesulit apa pun pelajaran matematika, seorang anak normal bisa menguasainya jika intensif belajar dalam dua bulan. Tapi pelajaran mengantri, butuh diajarkan bertahun-tahun untuk bisa diterapkan. Ada banyak pelajaran yang bisa didapat dari sebuah antrian. Seorang anak yang terbiasa antri, akan belajar disiplin, mengkalkulasi waktu, menghormati orang lain, serta belajar bersabar. Satu hal sederhana, tapi justru akan memberi pengaruh luar biasa pada kesuksesan seorang anak, kelak kemudian hari.
Kembali pada Ken. Dia memang punya kewarganegaraan Singapura, tapi sebagai orang Indonesia, jelas saya punya keinginan, kelak kami akan tinggal di Indonesia. Atau setidaknya dia bisa membagi apa saja yang dia punya untuk Indonesia, mengabdikan kemampuannya untuk Indonesia. Karena itulah, saya sering bercerita, tentang Indonesia, yang masyarakatnya butuh banyak bantuan. Tentang anak-anaknya yang tak seberuntung anak Singapura. “Jika kamu nanti jadi dokter, maukah kamu jadi dokter di Indonesia? Di pulau-pulau kecil,” kata saya, berkali-kali pada Ken.
Tapi dia selalu ingin jadi sekuriti. “I want to be chief security,” katanya soal cita-citanya kelak. Cita-cita ini, mungkin terinspirasi dari sekuriti di tempat tinggal kami di Perumahan Legenda Batam. Yang tiap malam punya “kuasa” memukul tiang listrik untuk memberi tanda soal waktu. Sesuatu yang mungkin dianggap keren oleh Ken, dan tidak ada di Singapura.
***
Ken, dan kecintaaanya pada negerinya, Singapura, adalah sebuah contoh kisah nasionalisme sederhana di keluarga kami. Ini bulan Agustus, bulan yang penuh nasionalisme bagi Indonesia, juga Singapura. Karena di bulan ini, kedua negera ini merayakan kemerdekaannya. Singapura pada 9 Agustus, sementara Indonesia 17 Agustus.
“Nasionalisme” kemudian menjadi kata sakral di bulan Agustus. Di Indonesia, di mana-mana: di pidato pejabat negara, di baliho caleg, di iklan komersial televisi, memanfaatkan momentum “nasionalisme” sebagai dagangan Di jalan keluar kompleks saya tinggal di Legenda, terpampang sebuah baliho caleg dengan semangat nasionalisme yang “berdarah-darah”. Seolah-olah negeri ini dalam kondisi perang melawan penjajah, dan nasionalisme perlu dikobarkan agar rakyat mau bersatu melawan penjajah. Padahal mereka-mereka itulah calon “penjajah” baru, yang benar-benar akan menyengsarakan kita.
Nasionalisme, benar-benar laris manis kayak kacang goreng saat layar tancap digelar. Apalagi menjelang pemilihan umum. Tapi, silahkan bertanya soal nasionalisme pada kuli gali lubang, tukang ojek, penyapu jalan, tukang parkir, petani kecil, atau nelayan yang hanya punya pompong kayu. Mereka tidak akan peduli soal nasionalisme. Yang mereka butuhkan adalah beras murah, transportasi yang mudah, atau sekolah yang baik untuk anak-anak mereka. Jika negara bisa menjamin kebutuhan mereka, dengan sendirinya nasionalisme akan tumbuh. Tak perlu dikampanyekan, apalagi lewat baliho-baliho caleg yang sok nasionalis itu.
Nasionalisme memang sensitif. Seperti isu SARA atau lainnya, disinggung saja sedikit soal nasionalisme itu, teriakan-teriakan “perang” mengumandang. Siapun tak suka disebut tidak nasionalisme, termasuk saya. Tapi benarkah kita sudah memetik manfaat nasionalisme itu sendiri? Sebagai hak kita sebagai warga negara di negeri demokrasi ini? Sebagai imbalan dari kewajiban yang telah kita berikan sebagai warga negara? Seperti nasionalisme anak saya, Ken, yang muncul dengan sendirinya karena melihat banyak kebaikan yang ada di Singapura.
Di Indonesia, sepertinya, untuk saat ini, yang menikmati dagangan nasionalisme, cuma “kelompok-kelompok” itu saja: politikus, birokrat, organisasi-organisasi massa semi-preman, dan orang-orang mapan yang “menggoreng” isu nasionalisme, untuk kemudian mereka nikmati sendiri. Rakyat kecil hanya dapat sisa, plus disuruh untuk “mencuci piringnya”. Nasi…, onalisme dengan sendirinya akan mendarah-daging di jiwa kita, jika harga nasi tak melambung tinggi.
Selamat menikmati Hari Merdeka! Merdekakan pula lah pilihan Anda!
Versi cetaknya di sini:
http://posmetrobatam.com/Topik/kolom/#axzz2cNmaFrTq