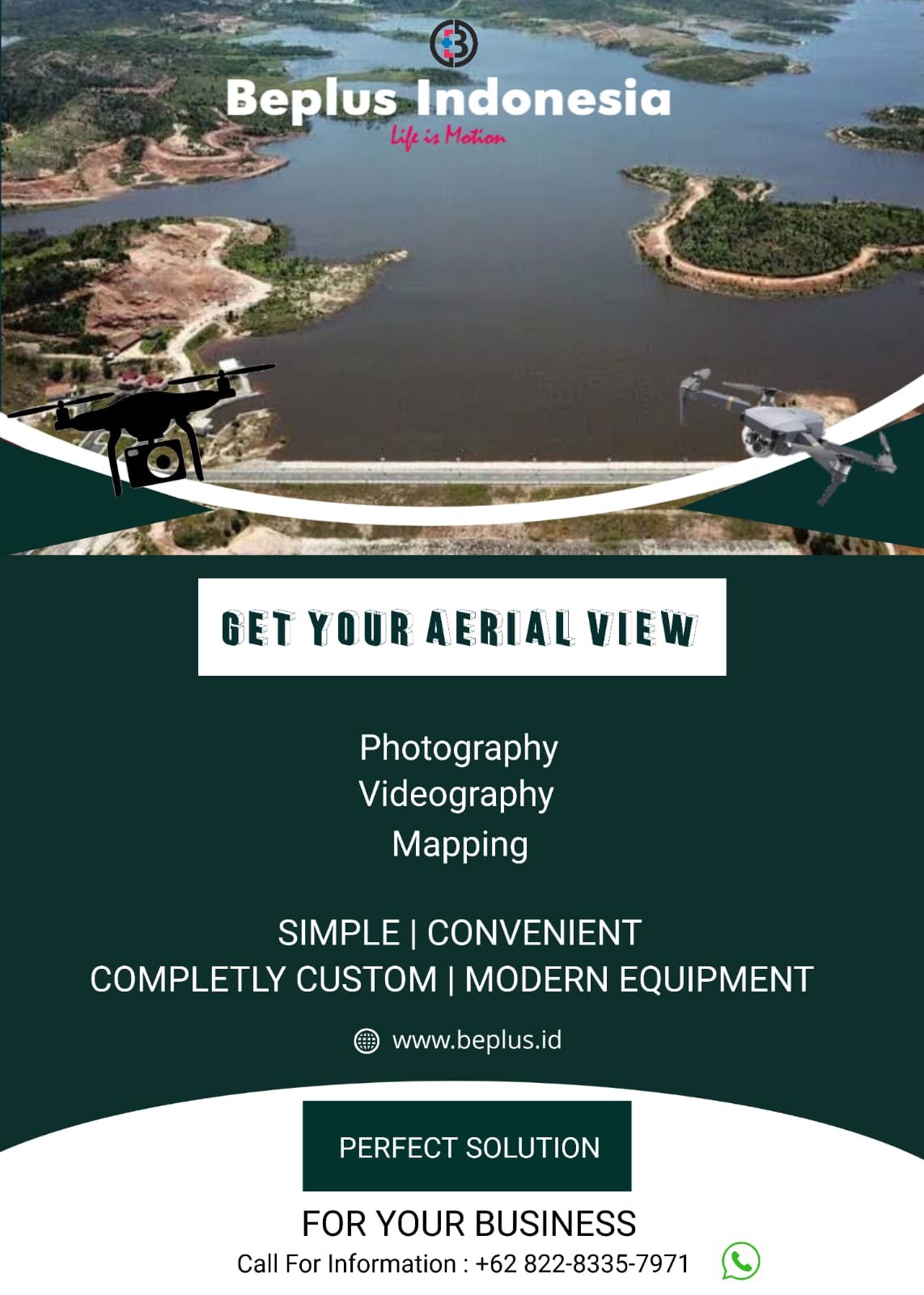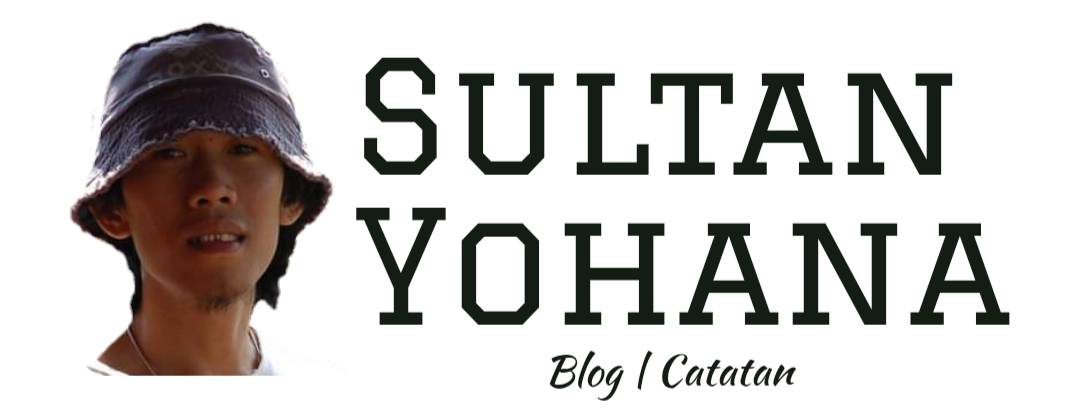Dia kelihatan gembira. Ipong, yang kawan lama itu, sembari duduk di atas kotak pendingin minuman kaleng milik pedagang kakilima, bercanda bersama rekannya. Ada tawa, cekikikan, umpat-umpatan, juga pukulan-pukulan kecil di antara mereka.
Malam yang ceria di sederet puluhan pedagang kakilima pinggir kantor walikota. Aku hampiri keduanya, mencoba mengemis kegembiraan.
”Om…,” Ipong selalu memanggilku demikian. Sapaan yang sangat membebankan. Ia menambahkan, ”bajunya bagus, merah-merah.”
Aku tak dapat menyembunyikan tawa ketika dari mulutnya keluar pujian terhadap baju, tepatnya t-shirt merah yang kukenakan. Pikirku, jangan-jangan berikutnya jins yang lututnya sudah deduel… del.. itu giliran peroleh pujian. Atau gelang monel yang melingkar di pergelangan tangan kanan. Khusus untuk gelang bermotif sederhana yang kubeli sehari sebelum aku memutuskan untuk bercinta dengan dunia, tercatat sudah ada tujuh orang yang memberi pujian. Tentu saja dengan satu pengharapan, gelang seharga 23 dolar ini akan berpindah tangan. Maaf! Yang ini tak akan terjadi.
Untungnya, dari mulut bocah satu SMP itu tidak keluar pujian-pujian berikutnya. Aku merasa lega. Terlebih ketika kedua bocah itu mengekor di belakangku, ketika aku masuk sebuah warung tenda. Saat itu, aku benar-benar butuh sedikit kegembiraan dari mereka.
”Aku bungkus saja ya, Om! Untuk emak. Tadi aku sudah makan, masih kenyang!” Ipong buru-buru menyusupkan kata-katanya, ketika aku memesan tiga ayam penyet untuk kami.
”Aku juga Om!” rekan Ipong ikut-ikutan.
Sementara pesanan disiapkan, kami mengambil duduk di meja nomor dua dari ujung paling kiri. Meja persegi seukuran satu meter persegi ini, bergelinjang, ketika tersentuh sedikit saja. Maklum, salah satu dari empat kakinya, tidak merata menyentuh tanah. Ipong dan rekannya mengambil duduk tepat di hadapanku.
Di meja sebelah kanan kami, dua orang pria paruh baya lahap menghajar nasi masing-masing, sepiring besar lele penyet, tempe, ayam, sayur-sayuran. Sesekali meneguki gelas-gelas bir minuman mereka. Selera yang aneh, pikirku. Lele penyet berkawan bir. Bir impor lagi.
Sedari berjalan tadi, celotehan keduanya mengalir seperti badai, memberikan kegembiraan luar biasa. Tentu saja kepadaku. Aku mencoba untuk tidak berkata-kata. Hanya mendengarkan keduanya. Hanya mendengarkan!
Kepada rekannya, Ipong menceritakan khayalannya: bagaimana seandainya Batam dijatuhi bom atom. Bagaiaman seandainya bom nuklir yang digambarkan Ipong sebesar meja di hadapan kami, dijatuhkan di Batam, bumi terbelah. Laut membuncah. Bukit-bukit berguguran. Gedung-gedung tinggi bertumbangan. Apalagi rumah liar mereka yang terdiri dari papan beratap seng karatan.
“Wuih…., pasti akan ada tsunami. Kalau sudah begitu kita mau tinggal di mana? Hih… ngeri! Pasti kita semua mati. Iya kan Om?”
Aku mengangguk.
”Memangnya kita bisa buat bom nuklir?” tanya rekan Ipong. Mendapat pertanyaan itu, bocah kurus yang seharusnya di waktu seperti sekarang ini berada di hangatnya dekapan keluarga, melirik padaku. Seakan minta aku untuk menjawab pertanyaan kawannya.
”Kalau Singapur pasti bisa!” rekan Ipong itu menghilangkan huruf akhir a ketika menyebut Singapura.
”Betul Om…” tanya Ipong. Aku kembali mengangguk.
”Wah bahaya dong!” rekan Ipong mengguncangkan tubuhnya. Menggidik sendiri.
”Tapi orang Singapur baik-baik, kok! Aku saja sering dibayar pakai dolar Singapura. Satu kali nyemir dikasih tiga dolar. Sudah berapa itu?” Cecar Ipong.
”Tapi mereka bisa buat bom nuklir!”
”Kita juga bisa buat! Iya, kan, Om!?” Aku mengangguk lagi.
Namun, sebelum perdebatan Ipong dan rekannya berlanjut, tiga ayam penyet sudah tersiapkan. Sebuah, di atas piring untukku. Dan, dua bungkus yang di dalam kresek untuk mereka berdua. Ipong segera bangkit dan menerima bungkusan itu. Sesaat beradu pandang dengan temannya, sebelum kemudian bersama mengucap terimakasih dan berlari.
Sekali lagi aku mengangguk. Menerima kegembiraan terakhir dari mereka, sebelum akhirnya sebuah SMS brengsek menghancurkan semuanya.
(Batam, 6-7-2006)