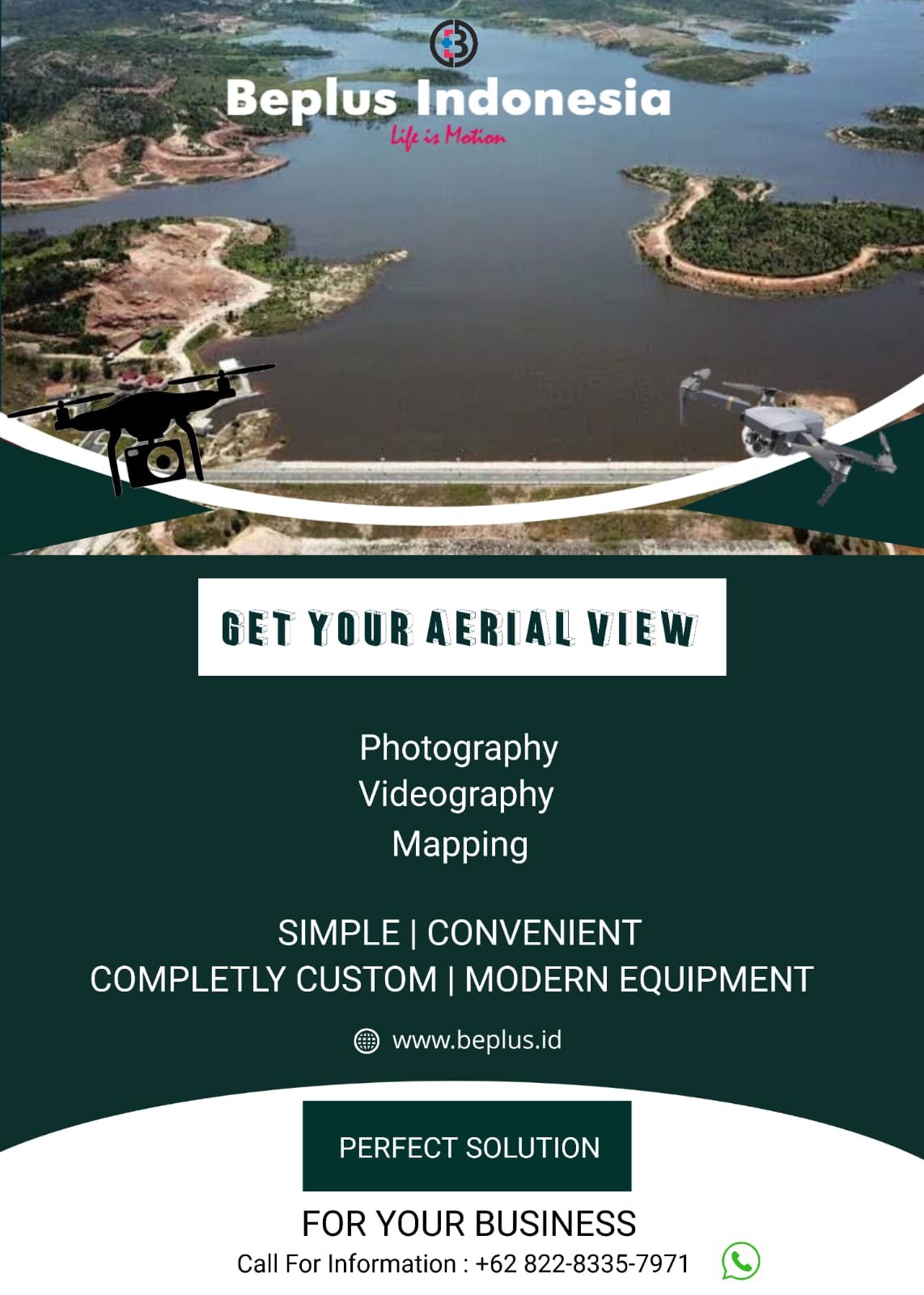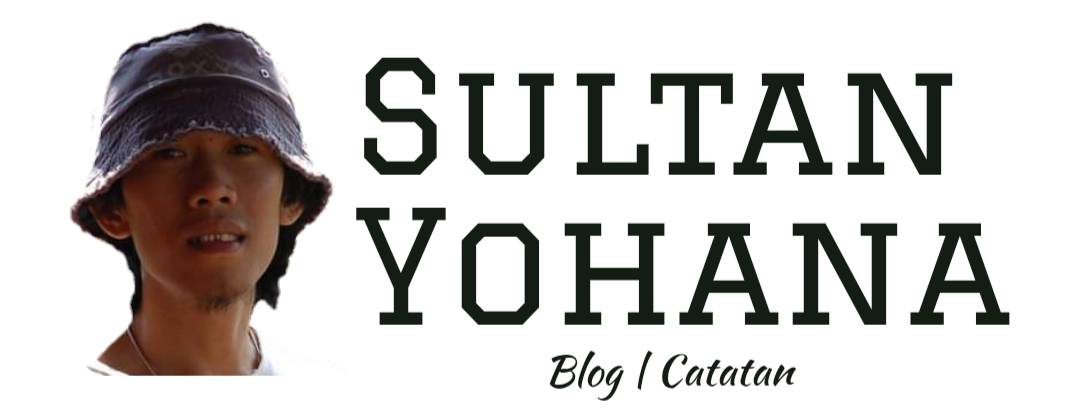: dan nenek saya yang okem
Almarhumah nenek saya, Rafiah, meninggal di usia 90-an. Kami tidak bisa memastikan usia sebenarnya, karena tak ada catatan kelahiran. Yang jelas, beliau “menangi” jaman Belanda, Jepang, PKI, Soeharto, serta jaman Jokowi. Pada cucu tersayangnya, ya tentu saja saya, nenek sering mendongeng apa-apa yang terjadi di jaman-jaman itu. Kadang, sore-sore sembari menunggu adzan Maghrib, sambil duduk nyante di kursi tamu, saya biasa tiduran di pangkuannya. Sambil mendengarkan nenek mendongeng.
Beliau tidak pernah kehabisan bahan untuk mendongeng. Cucunya banyak. Tapi, saya merasa paling beruntung menjadi cucu yang paling sering didongenginya. Mungkin karena memang saya cucu yang paling lama tinggal sama beliau. Sejak ibu saya menikah lagi dan tinggal di rumah suaminya, saya memilih tetap tinggal bersama nenek. Berdua saja. Cucu-cucunya yang lain, paling datang di Hari Raya, atau mampir sak nyuk saja.
Nenek saya adalah tipikal “orang jalanan”. Sejak muda sudah terbiasa mengadu nasib di pasar-pasar, mbabu, atau “ngenger” ikut orang. Hanya untuk bisa mempertahankan hidup. “Nenek okem” istilah Iwan Fals-nya. Kawan pasarnya banyak banget, belum lagi kawan pengajian di Muslimat (beliau menyebut pengajian setiap Senin dan Kamis sore dengan “musyawaroh”).
Kalau belanja ke pasar, bim salabim…. duit seuprit bisa dipakai beli banyak barang. Kawan-kawan lamanya, kerap memberi gratis atau menjual murah padanya. Tapi ya itu, sebagai gantinya, mereka biasanya ngobrol lamaaaaaa… banget. Bercanda-canda, bercengkerama dulu. Berkabar ini-itu dulu. Ke pasar bisa empat-lima jam, meski jarak dari rumah cuma sepelemparan batu. Saya yang dulu biasa ikut ke pasar, sering ngamuk-ngamuk kalau sudah nunggu nenek ngobrol sama kawannya.
Eits…, semasa muda dia juga cantik. Katanya nenek sih. Karena ndak ada banyak foto dokumentasi, saya tak tahu pasti. Satu-satunya foto waktu dia masih muda, pernah saya pergoki, dan memang beliau sedikit-sedikit mirip Arab, arapatigenah maksudnya, hehehe. Tubuhnya kurus langsing mirip saya. Kulitnya, cukup bersih dan cerah, tidak hitam pekat seperti kawan-kawan melaratnya yang lain. Hidungnya, yang paling menjadi daya tarik, terbilang mancung untuk ukuran hidung orang Jawa yang pesek-pesek. Nenek juga pernah bercerita pada saya, dia sempat dilamar lelaki yang kemudian belakangan jadi lurah desa tetangga. Tapi ditolak buyut saya, Siti Aminah. Kerana menganggap si lelaki bukan dari golongan kami. Si lelaki dari golongan priyayi abangan, yang takut akan menjadikan nenek saya “istri babu” saja.
Keluarga kami memang “keluarga sudra”. Keluarga melarat tanpa punya sumber penghasilan apa pun seperti sawah atau sebangsanya. Hanya otot dan otak yang kita punya. Saking susahnya, satu anak nenek bahkan direlakan untuk diadopsi tetangga.
Ketika jaman Belanda, nenek sempat “mburuh” di keluarga Belanda di kampung kami. Dalam cerita-ceritanya pada saya, nenek masih begitu hafal nama-nama orang Belanda yang jadi tuannya itu. Kakak-beradik “Ndoro Branget dan Blanger”, begitu nenek biasa menyebut. Dan setiap menceritakan dua orang ini, selalu ada nada kekaguman di kata-kata nenek tentang sosok dua tuan Belanda itu. “Wonge alusss lan gak tegooan. Lek ketok wong ndokar mecut jaran ndik ngarepe, langsung wong ndokar iku diseneni. Gak oleh jaran dilarani ngono,“. Kira-kira kalau saya terjemahkan begini, “orangnya (dua tuan Belanda) itu lembut dan tidak tegaan. Kalau melihat ada kusir dokar mencambuk kuda, kedua tuan itu langsung memarahi si kusir. Tidak boleh kuda diperlakukan kasar seperti itu.”
Di jaman Belanda pula, nenek bercerita, semuanya aman. Masyarakat bebas memilih keyakinan mereka. Kesehatan masyarakatnya diperhatikan. Mantri-mantri Belanda biasa keliling kampung untuk mengecek kesehatan masyarakat, bahkan ngecek kesehatan ternak masyarakat. Makanan tercukup, jalan-jalan bagus, dan kalau ada maling, biasanya cepat tertangkap.
Sebetulnya, kehidupan “masyarakat sudra” jaman itu seperti halnya yang diceritakan nenek, tidak peduli apakah Belanda atau siapa yang menjadi penguasa. Karena tokh, siapa pun yang berkuasa, mereka cuma berpikir soal hal-hal sederhana saja. Berkecukupan akan makan, kesehatan, dan rasa aman. Pendidikan, bagi orang seperti keluarga kami, ketika itu, tidak dipikirkan. Beruntung anak-anak nenek, semuanya bisa disekolahkan di madrasah. Meskipun untuk itu, ibu saya misalnya, harus jadi “mburuh” sekaligus mondok dan ngaji di satu keluarga pemilik pesantren yang membiayai uang sekolah ibu di madrasah.
Di jaman Jepanglah, seperti yang nenek ceritakan, hidup serba susah. Masyarakat diwajibkan “menyembah” matahari setiap pagi, termasuk nenek. Tentara-tentara Jepang juga serakah, dan kerap menjarah bahan-bahan makanan masyarakat. Menjarah panen masyarakat. Nenek bahkan sering menceritakan bagaimana ia harus menyembunyikan telur ayam kampung miliknya. Karena tentara Jepang kerap datang dan minta paksa telur ayam.
Tapi, di jaman Jepang itu pula, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik orang seperti nenek. Semisal disiplin dan kerja lebih keras, serta kesadaran diri bahwa “dijajah itu sama sekali tidak manusiawi”.
Di jaman Soekarno, seingat saya nenek cuma mengisahkan banyak euforia-euforia kemerdekaan saja. Rame-rame ikut pawai ini-itu, pokoknya yang heroik-heroik. Bagaimana ia bercerita soal gembiranya menyambut Soekarno ketika datang ke Malang, sembari sangu sebutir semangka, yang sialnya, jatuh dan terinjak-injak saat pawai.
Di jaman PKI, saya selalu diceritai kisah-kisah sedih. Bagaimana tetangga-tetangga yang dituduh orang PKI “dihilangkan” paksa, disembelih, dan dikubur massal. “Ojo dulinan ndik nggon iku, biyen nggen’e kuburane PKI” begitu biasa nenek berpesan pada saya ketika saya “ngalas“, main ke tempat yang terlalu jauh dan dianggap wingit/angker.
Di jaman Soeharto, tak banyak cerita dari nenek; ya karena sebagaian besar usia saya sudah langsung mengalaminya. Tapi yang jelas, sejak jaman Belanda hingga meninggal dunia, tidak ada yang terlalu berubah dalam kehidupan nenek. Ya, hidup tetap begitu-begitu saja. Tetap jadi “kaum sudra”. Kalau mau makan ya kerja keras. Pemerintah manapun ndak bisa diandalkan. Semuanya sama saja. Yang kaya diperlakukan baik, sementara yang miskin cuma diperhatikan kalau mau pilkada. Yang kaya bebas berbuat apa saja, sementara yang miskin salah sedikit masuk penjara.
***Hidup nenek dari jaman ke jaman, pergaulannya yang luas di kalangan sesama “masyarakat sudra”, membentuk banyak hal menarik padanya. Nenek saya misalnya, meskipun kami bukan keluarga seniman (bahkan di daerah kami pertunjukan wayang kulit dianggap tabu), sangat pandai menyusun parikan secara spontan. Beri dia satu kata, dia akan dengan cepat mengembangkannya ke dalam empat baris kalimat parikan yang nadanya enak didengar, sekaligus isinya keras menyindir.
Hal lain yang menarik yang saya ingat adalah penggunaan kata “POLITIK” dan “KOMUNIS” dalam kosokata sehari-hari nenek. Saya kerap tertawa-tawa sendiri jika mengingat-ingat nenek menyebut-nyebut dua kata itu, ketika dia sedang marah. Kata “POLITIK” misalnya, biasanya dipakai sebagai “kata kerja” untuk merujuk pada seseorang yang hendak menipu nenek, atau membohonginya. Atau kepada tokoh-tokoh masyarakat, semisal pengurus arisan pengajian yang kadang kerap menilep uang anggotanya.
Atau untuk orang yang tidak pernah menepati janji. Semua itu, biasa dirangkum nenek menjadi satu kata analogis, yakni: POLITIK(us).
“Koen ojok politik-politik karo aku yo! Koen pikir aku ora ngerti,” begitu biasa nenek mempergunakan kata “POLITIK” dalam percakapan sehari-hari. Tidak peduli orang yang berbohong/hendak menipunya adalah anak-anak sendiri atau orang lain, semuanya pasti akan disebut “POLITIK” jika berani-berani hendak memperdayanya.
Kata “KOMUNIS” lain lagi. Nenek biasanya menggunakan kata ini untuk melabeli orang-orang jahat yang tidak lagi sedang/hendak menipu. Tapi sudah menipu atau berbuat jahat. Kata “KOMUNIS” tidak lagi diasosiasikan pada kelompok-kelompok kiri yang sempat berbagi kuasa di Indonesia. Tapi mendiang nenek saya, akan memakai kata itu pada siapa pun orang-orang jahat. Tidak peduli yang rajin sholat atau tidak, jika suka merusak/menipu/berbuat jahat, nenek biasanya dengan mulutnya yang terkenal “ngablak“, akan mengatai-ngatai orang itu sebagai “KOMUNIS”.
Di pikiran nenek, kata “politik” dan “komunis” itu sama jahatnya. Sama merusaknya. Dan di jaman sekarang ini, saya kian yakin akan keyakinan nenek. Saya tidak suka komunis karena ini tidak sesuai dengan hukum Illahi; tapi saya juga sangat membenci politik(us) yang sekarang betul-betul merusak Indonesia dengan massif.
Lewat politik(us) lah kini undang-udang negara diperjual-belikan, kekayaan negara diobral, kapitalisme biadab diterapkan. Masyarakat Indonesia, meski kelihatan makmur-makmur, tapi hampir semua sumber daya mereka terjarah kapitalisme. Sekolah-sekolah dikapitalisi, kepentingan umum diserahkan ke kapitalis. Alhasil, semua yang ada di Indonesia, tidak ada lagi yang gratis, sekalipun itu kekayaan negara yang seharusnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kapitalis, di jaman sekarang, justru jauh lebih “kejam”, lebih mematikan, lebih serakah, dan lebih merusak. Politik(us)lah yang paling berperan di sisi itu.
Saya tidak bisa benar-benar menyalahkan nenek, semasa hidup. Bahwa penggunaan kedua kata itu salah. Tentu saja saya juga tidak pula ingin meralatnya. Malah justru bisa membuatnya bingung. Saya lah yang muda, yang harus dituntut untuk memahami kata-katanya. Mengguyoninya ketika beliau marah, atau mendengarkannya dengan sabar ketika beliau bercerita. Karena semua orangtua yang baik, tidak pernah meminta apa pun hal material pada anak-cucunya. Yang mereka butuhkan hanya perhatian, dan didengar kata-katanya. Itu saja.