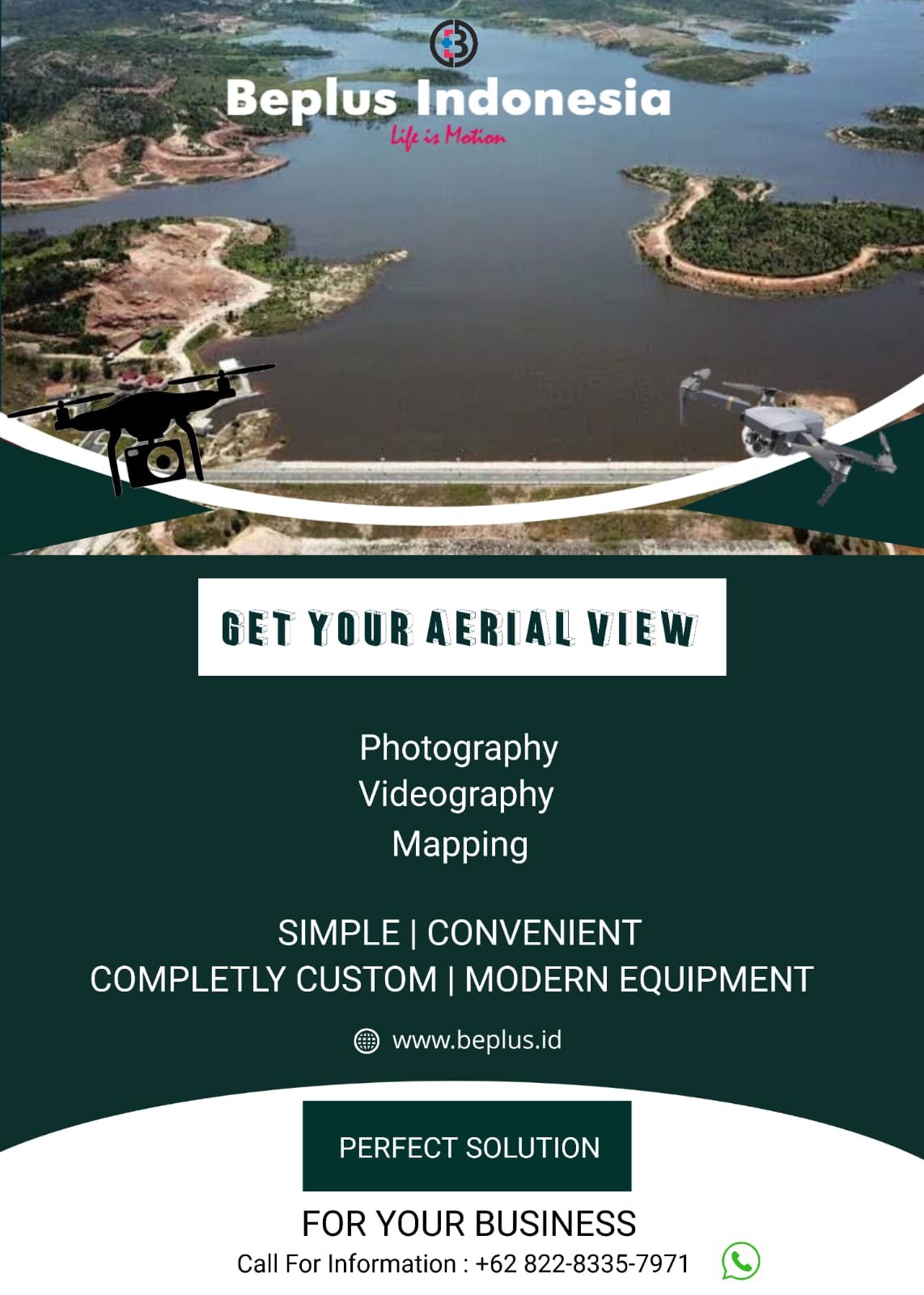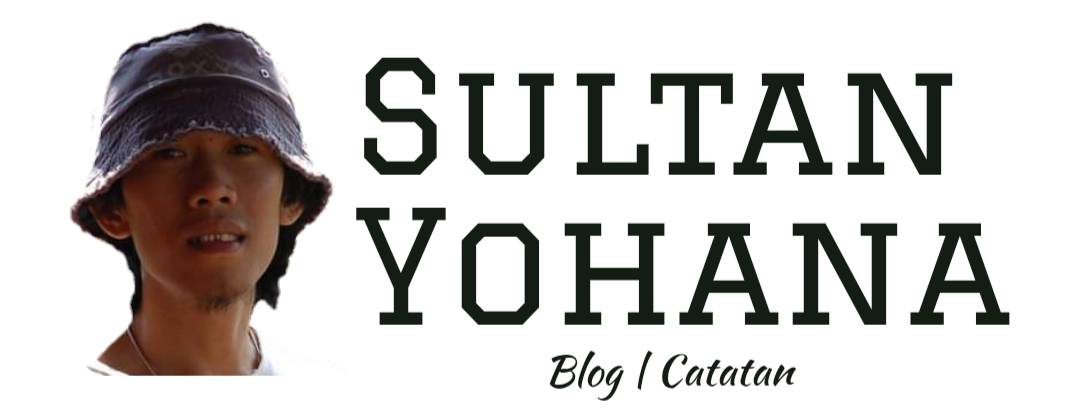: Karena anak kita bukan kita.
Seperti umumnya anak “jaman sekarang”, kedua anak kami, Ken dan Zak, juga senang iPad, gemar berselancar internet, juga hobi main game. Dan sudah menjadi tabiat “anak internet”, emosi keduanya cepat naik, tidak sabaran, serta jarang memberi perhatian pada sekelilingnya. Hal-hal yang kadang memunculkan kekhawatiran saya.
Tapi bagaimanapun, dunia maya, massif manfaatnya. Kita tidak seharusnya LUPA, dan kudu memberi APRESIASI yang tinggi, anak-anak “jaman sekarang pintar-pintar, cepat belajar; tiba-tiba saja mereka bisa mengenal huruf. Tiba-tiba bisa membaca, bisa menulis, serta sanggup tahu tentang isu-isu mutakhir. Siapa menduga, Ken, sudah cukup bisa membicarakan Donald Trump, presiden USA yang kontroversi itu.
“Saya tak akan memilih presiden yang rasis (menunjuk pada Trump),” katanya satu malam ketika kami bersantai di ruang keluarga. Kesempatan seperti ini, langsung saya manfaatkan untuk menjelaskan soal rasisme, soal hakikat perbedaan, soal fitrah keberagaman. Soal ke-Tuhanan. Bagi saya pribadi, menyenangkan sekali, mengetahui anak berumur 10 tahun sudah paham tentang rasisme, menyadari tentang bahayanya rasis. Dan semua itu dia tahu dari internet.
Awalnya, sebagai bapak yang hampir sepanjang hari menghabiskan waktu dengan mereka, saya khawatir dengan semua yang berbau game, internet, HP pintar, tablet, maupun komputer. Saya sempat membatasi secara ketat akses anak-anak terhadap benda-benda itu. Tapi, sebagai orang yang banyak “bekerja” dengan internet, akhirnya saya HARUS menyadari. Dunia telah berubah begitu cepatnya!
Apalagi saya tinggal di Singapura, negara yang begitu “mendewakan” tekhnologi. Begitu tergantung pada tekhnologi. Hampir semua aspek kehidupan di sini, tekhnologi berbasis on-line telah diterapkan. Naik bus, meli makan di warung, butuh tekhnologi internet. Beli kolor di Carousell juga. Bayar ini-itu dengan butuh tekhnologi on-line, bahkan sebagian cara belajar si Ken pun, kini telah disesuaikan dengan tekhnologi. Sebagaian pekerjaan rumahnya, telah dialihkan ke on-line.
Fakta ini kemudian “membenturkan” saya pada dua pilihan: apakah akan membawa anak-anak ke dalam aturan “Korea Utara” atau “USA”. Pilihan yang sulit memang, tapi bagaimanapun, harus memilih salah satunya. Pada akhirnya, saya memang harus memilih pilihan terakhir. Meskipun efek yang akan datang, juga tak kalah bahayanya, tapi saya tidak ingin menjadi orangtua yang “tidak tahu diri”. Yang memaksa “ikan hidup di gurun pasir”. Meski harus mengawasi ketat dan selalu waspada pada perubahan perilaku anak-anak. Pada akhirnya saya membolehkan kedua anak saya bermain dan mengakses internet dengan baik. Meski, tentu saja, masih ada batasan dan waktu yang kami tetapkan. Serta memberi “keamanan ekstra” pada iPad atau komputer yang biasa mereka mainkan.
Dan, memang butuh begitu banyak tenaga dan kreatifitas untuk terus membuat anak “bergerak” dan sedikit melupakan “dunia on-line” mereka saban hari. Saya biasa memilih berkegiatan luar ruang, menyediakan banyak mainan alternatif sebagai pengganti, melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan kini, saya kerap mengajak anak-anak “berbisnis” dengan ikut saya ketika saya bertemu dengan pembeli/penjual untuk bertransaksi. Kegiatan ini, sungguh, sebagai orangtua, sangat menguras tenaga. Capek sekali, dan tidak menyenangkan. Anda bisa bayangkan, saya saban hari harus duduk, memelototi, dan ikut bermain mobil-mobilan dengan Zak di lantai. Ikut serta masih dalam imajinasi anak-anak. Atau pura-pura kembali menjadi anak-anak, adalah salah cara saya untuk tidak bosan ketika Ken atau Zak mengajak saya bermain mobil-mobilan atau perang-perangan.
Mahal? Ya benar! Membeli sebuah mobil-mobilan tak jarang harganya jauh lebih mahal ketimbang membeli game on-line yang bisa didownload hanya dengan beberapa sen saja. Tapi begitulah dunia. Seaidainya keluarga kami tinggal di desa di kota asal saya di Singosari, Malang; mungkin ceritanya akan beda. Anak-anak saya mungkin akan saya ajarkan trik-trik mancing belut, membuat perapian untuk membakar singkong curian di tegalan. Atau mengajarkan menangkap udang dengan tangan, juga keahlian memanjat pohon agar bisa memetik buah-buahan liar yang biasa tumbuh di pinggir-pinggir tegalan untuk bermain sekaligus mencukupi nutrisi/vitamin tubuh.
Tapi, saya tidak lagi tinggal di desa!
Kita harus menyadari, dan menerima, anak “jaman sekarang” berbeda banget dengan anak “tempoe doeloe”. Tentu sangat tidak BIJAKSANA, kalau kita membandingkan dua dunia itu, apalagi memaksakan “cara lama” serta menganggap semua yang ada di masa silam adalah lebih baik ketimbang jaman sekarang. Setiap jaman ada sisi baik sekaligus sisi jahatnya. Tergantung bagaimana kita menyerap sebanyak mungkin sisi baik itu, serta menangkal sebisa mungkin sisi buruknya.
Salah satu hal TERKERAS yang saya ajarkan pada kedua anak saya adalah, “kebiasaan meminta maaf” sekecil atau seremeh apa pun sebuah kejadian. Minta maaf kepada siapa pun, di manapun. Karena saya sadar, “jaman sekarang” meski sederhana, tapi kata MAAF sungguh sangat sulit dilakukan. Padahal kata ini, begitu “saktinya”; sanggup meruntuhkan sebesar apa pun kebencian, jika permintaan maaf dilakukan secara tulus tanpa tendensi.
Anak kita bukan kita! Jaman saya dan jaman anak saya jelas beda!