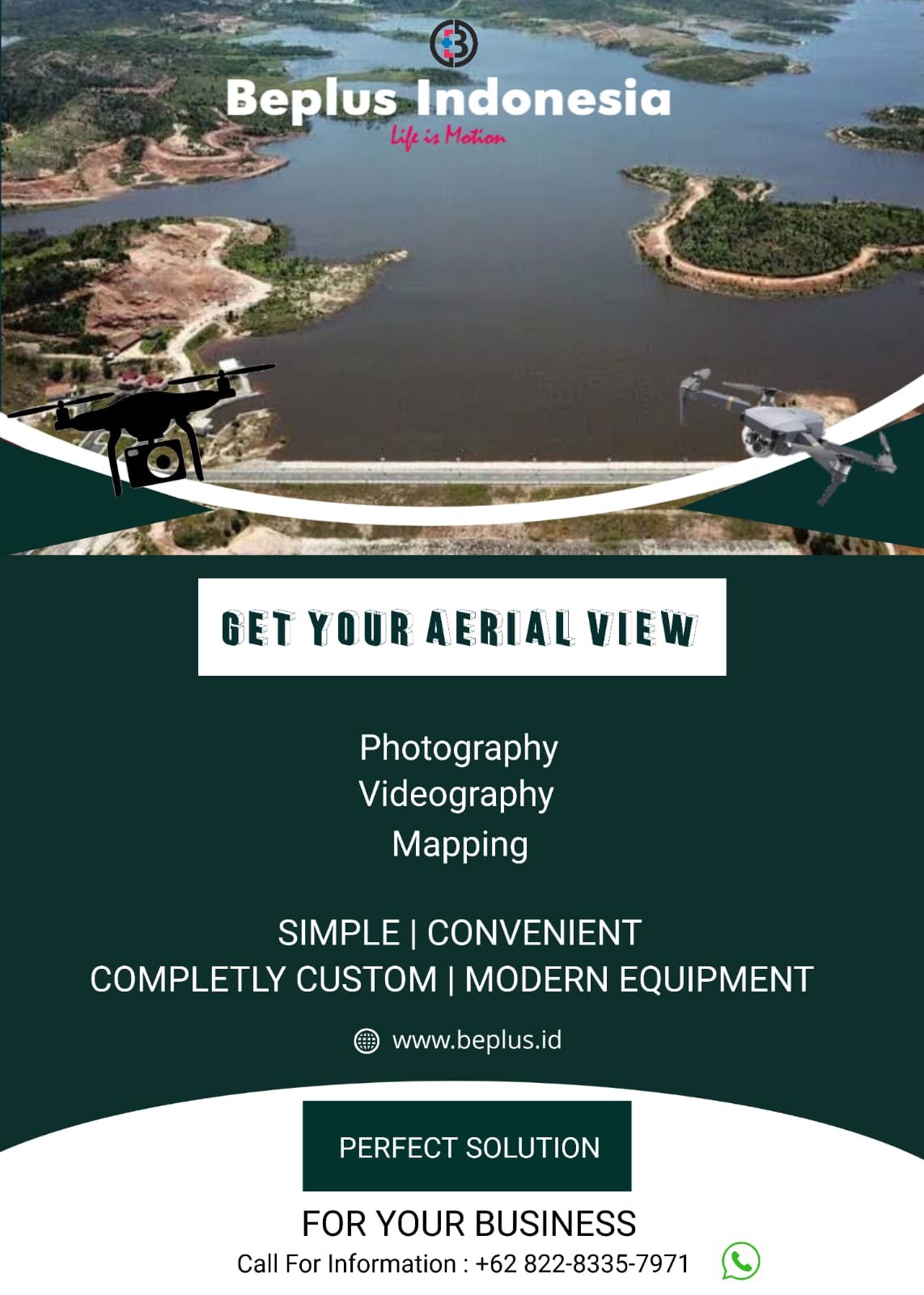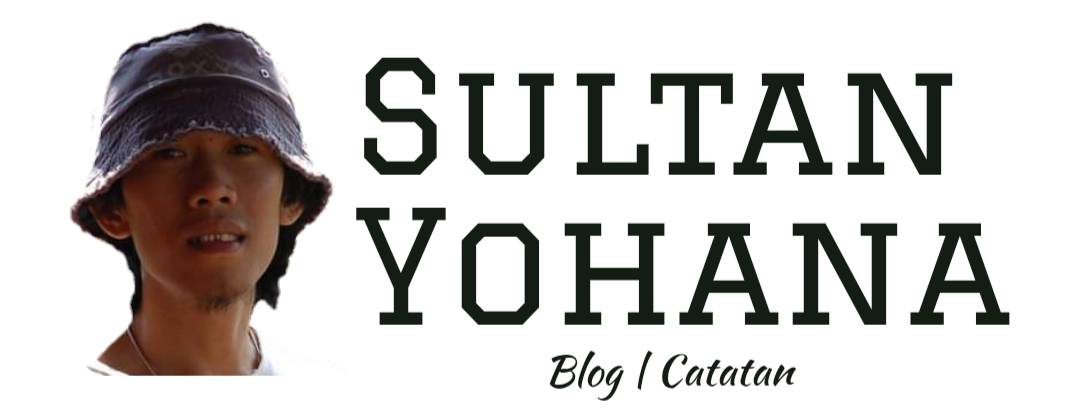I Am Ethnic, 2001. Berbalut kulit kambing yang menutup hampir seluruh bagian tubuh Mella Jaarma, sang artis, menggelontarkan tanya: secepat apa sebuah pakaian yang biasa melekat di tubuh kita menyelesaikan fungsi sosialnya?
Jawabannya? Tentu ada pada Anda masing-masing.
Tanya Mella yang dibikin enam tahun silam itu, saya pastikan menarik mata setiap orang yang hendak mudik ke Batam dari Singapura yang lewat Pelabuhan Harbour Front. Tanya itu, juga Mella yang berbalut kulit kambing, apik nampang di neonbox yang didominasi warna kuning yang nangkring di dekat pintu keluar pelabuhan. Menyenangkan, melihat karya orang Indonesia di negeri tetangga. Sayangnya, ketika kaki menginjak Pelabuhan Batamcentre, yang tersapa malah baleho iklan besar-besar. Gambarnya, luar biasa bergaya pejabat Indonesia, norak dan full kapital: Tiger Beer.
Kembali pada Mella yang berbalut kulit kambing. Ketika mencoba memfoto neonbox itu, telinga saya menangkap obrolan seorang apek dengan seseorang lewat HP. Siapa yang diajak bicara? Tebak saja!
”Kalau boleh tahu, bojomu orang mane? Heheh…, emangnya berapa umurnya?”
Sepenggal obrolan itu memastikan saya (pembaca di luar Batam mungkin kurang mengerti akan situasi seperti ini) bahwa yang diajak bicara apek 50-an tahun itu seorang wanita muda, warga negara Indonesia bersuku Jawa, dan yang pasti, sudah tidak perawan!
Tidak perawan? Apa pula ini? Sembari berdesakan mengantri check boarding, apek itu terus saja mengumbar obrolan di telepon. Saya berdiri tiga badan di belakangnya. Obrolannya, tentu masih jelas terdengar. Ya, Nagoya! Wanita di seberang telepon tinggal di Nagoya. Mencari wanita perawan di Nagoya yang berasyik telepon dengan apek Singapura, inilah yang memastikan saya wanita di seberang sudah tidak perawan. Terdengar sarkastik memang. Tapi jika Anda orang Batam, juga sering keluar malam, dan tiap minggu keluar masuk Singapura-Batam, Anda akan menyetujui dugaan saya. Ini Batam! Bukan Jakarta bukan Surabaya. Apalagi Malang yang berudara dingin menggigit.
Di atas kapal Batam Fast yang akan menyebrang ke Batam, saya sudah ogah mendekati sang apek. Saya pilih duduk di dek atas bersama para perokok, sementara sang apek memilih di dalam. Di ruang ber-AC sembari menenggak kaleng-kaleng Carlsberg.
Tokh, satu kesimpulan sudah saya dapat. Dan konfirmasinya, satu jam lagi, ketika memastikan si penjemput apek tersebut. Apakah wanita bergincu tebal dengan tanktop dan jins membalut ketat pantat atau tacik berwajah sangar. Jika yang pertama yang menjemput, saya pastikan dugaan saya 100 persen tepat.
Kapal berangkat. Menderu. Menyisakan kepul asap solar dan buih putih yang menggelorakan. Tangkas kapal menyusur, melewati pulau-pulau kecil bagian selatan Singapura dan juga, berpuluh kapal besar yang tengah buang jangkar. Ketika mata saya tertuju pada onggokan pulau-pulau yang tengah direklamasi, tiba-tiba ingatan saya mengalir menuju tiga tahun silam.
Huh…, ini pulau direklamasi menjadi secantik bidadari. Di atasnya, dibangun resort-resort nan indah yang aku yakin, sewa per malamnya berharga ratusan dolar Singapura. Apalagi mungkin, penyewanya konglomerat-konglomerat Indonesia. Tiga tahun silam, saya ingat betul, ketika seorang budak lelaki berumur empat tahun, tenggelam dan tewas di kubangan bekas galian pasir di Batu Besar, Batam. Mungkin, salah satu pulau secantik bidadari itu, pasir reklamasinya berasal dari Batu Besar. Yang telah merenggut nyawa budak kecil itu.
Kapal yang saya tumpangi terus menderu. Sejenak saya bersyukur dengan pelarangan ekspor pasir darat dan segala bentuk galian jenis C dari Kepulauan Riau. Menurut saya ini sebuah keputusan yang tepat. Bukan karena rasa sentimen saya terhadap kemakmuran Singapura, melainkan kerusakan alam yang teramat parah yang dihasilkan dari penggalian tersebut yang saya sesalkan.
Kapal yang membawa saya sebentar lagi memasuki perairan Internasional. Lamat terlihat seratus meter di ujung kanan sana, sebuah tug boat melaju pelan ke arah dari mana saya berangkat tadi. Di belakangnya, diancok…, segepok pasir, yang dari mana lagi, kalau bukan dari Kepulauan Riau.
Saya terheran. Kalau di Minggu (8/4) siang bolong kayak begini kapal pembawa pasir bisa lolos dengan enaknya, lalu di mana para penegak hukum kita? Yang kemarin-kemarin nyerocos tiada habis di media: Ganyang pengekspor pasir ke Singapura!

Ah, sudahlah! Soal pasir, itu bukan urusan saya. Saya mungkin hanya bisa berdoa, orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kerusakan alam, termasuk penegak hukum yang enak-enak bobo siang, jaksa-hakim yang makan uang suap, juga wartawan yang suka bela pengusaha penambang pasir, hidup mereka tak akan tenang. Semoga dalam mimpi-mimpi mereka, arwah budak-budak kecil yang meregang nyawa karena kubangan penggalian pasir, mendatangi mereka. Menakuti mereka. Hingga mereka tak sempat lagi bersetubuh ria! Amien…