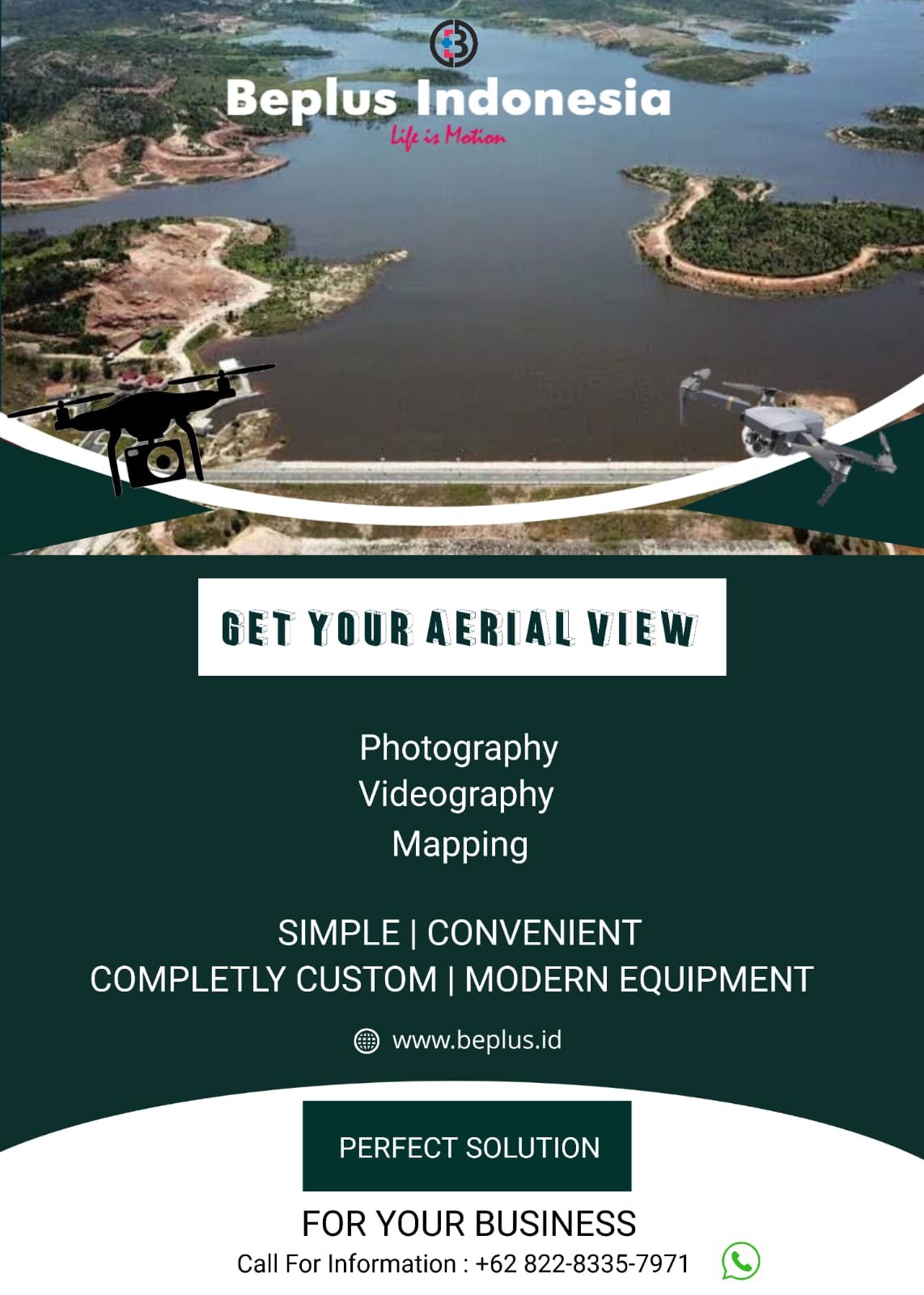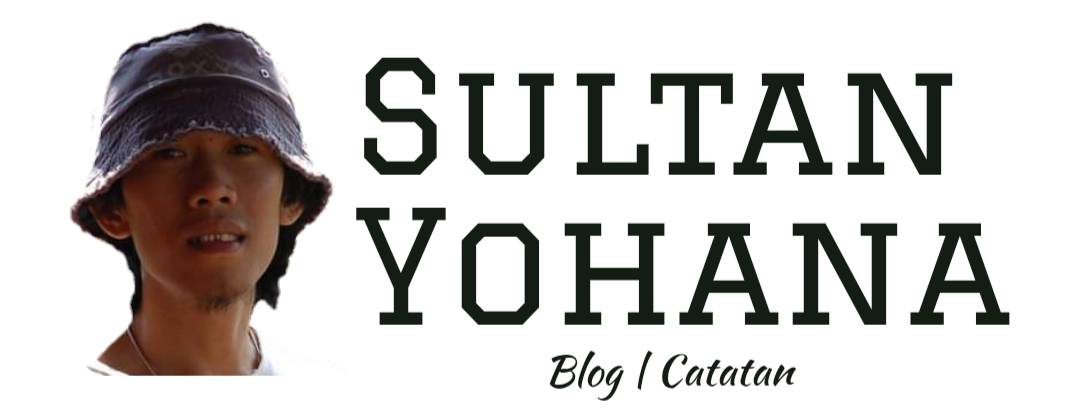Suatu malam menjelang dini yang cerah. Di warung mie rebus depan masjid raya, Nasirun bercerita pada saya. Katanya, matahari siang sekarang, jauh lebih ramah dibandingkan dengan aparat pemerintah. Lho?
“Semua kebijakan sepihak! Ratusan ribu orang, diberangus pekerjaannya, sementara pemerintah sama sekali tidak mencarikan penggantinya.” Terus terang saja, saya sepaham dengan pedagang sate Padang keliling ini. Sekarang, yang lagi ngetrend, pemerintah mengadakan acara berangus memberangus-an. Pedagang kaki lima, judi, prostitusi, calo, dan segenap pekerjaan yang dianggap oleh mereka, mengganggu
pemandangan indah, sebuah kota.
“Intinya, Abang setuju dengan prostitusi dan judi? Juga PKL atau calo?” Tanya saya.
“Kalau dibilang setuju, nanti terjerat pidana! Lebih parah lagi, dikira subversif! Melawan negara! Melanggar undang-undang! Memang sih, sekarang tidak ada culik menculik. Tapi, apalah artinya seorang saya? Apakah setuju atau tidak, bukan masalah!” Mantap juga bahasa bapak satu ini. Mungkin terlalu banyak baca suratkabar atau nonton Liputan 6.
“Yang jelas sekarang, sekilo daging dagangan saya, tidak pernah habis dalam semalam. Dulu, dua kilo ludes tak tersisa,” ia meneruskan keluh kesahnya.
“Empatpuluh ribu sehari, sekarang sudah tidak terkejar! Itu pun masih harus putar-putar cari sewa,” kali ini yang angkat bicara Temiang. Lelaki beranak dua, yang bangga, tapi dulu, menyebutkan profesinya sebagai tukang ojek profesional.
“Ah, lagi-lagi keluh kesah!” potong ibu pemilik warung.
Saya hanya tertawa.
“Apa-apa diberangus! Tapi tidak secuilpun pekerjanya dicarikan kerjaan pengganti. Padahal, berapa puluh ribu yang bekerja menggantung di sana!” Suara Nasirun kembali
membuncah. Malam yang cerah, berangsur-angsur menggigil. Oleh keluh kesah mereka.
“PKL-PKL dipaksa pindah ke tempat sesunyi kuburan! Mana ada yang mau mereka?” Temiang menimpali.
“Pelacur-pelacur ditangkap lalu kerangkeng tanpa tersedia pembalutnya wanitanya!” beber Nasirun. Ibu pemilik warung cemberut. Mungkin mendengar kata pembalut!
“Belum lagi calonya? Orang yang bekerja di tempat judi?” Lagi, Temiang bersuara.
Saya kembali tertawa. Dan mereka kecewa.
“Mak, tiga batang gepe lagi-lah! Bekal sebelum tidur!” Ini teriakan Temiang kepada ibu pemilik warung. Setelah itu, dengan motor bututnya, Ia pun sirna.
Bersamaan itu pula, Nasirun menyeruput kopi di depannya. Sebelum seteguk air hitam itu masuk ke kerongkongannya, terlebih dahulu dicecapnya di mulut. Mungkin menikmati
pahitnya gerunjel bulir-bulir kopi yang tak pernah halus tergerus. Maklum kopi murahan.
“Mamak selalu gembira ketika aku pesan kopi yang pahit,” dedah Nasirun lagi. Seperti tahu apa yang saya pikirkan. Mamak yang dimaksud, ibu pemilik warung, hanya tersenyum. “Ah, kayak tak tahu saja! Harga gula sekarang di atas kantor pemerintah! Tinggiiiii… sekali,” sela ibu pemilik warung.
“Kok, di atas kantor pemerintah, Bu?” Tanya saya.
“Lho-lho…, kantor pemerintah kita kan tinggi sekali! Tujuh lantai lagi! Saya saja belum pernah memasukinya! Tak berani. Katanya angker! Banyak hantunya! Masuk pakek sandal saja tak bisa?! Apalagi pakek celana rombeng? Padahal, tinggal itu yang kita punya! Padahal kan, itu milik kita semua! Padahal lagi, lho… kan, mbangunnya dari uang kita! Pajak dari kita! Kita beli rokok, kena pajak! Naik teksi, ditarik pajak! Nonton bioskop, dipajakin! Makan di warung, masih saja!” Ibu pemilik warung itu nyerocos dengan semangatnya.
“Ohh…” mulut Nasirun melongo.
Saya pun spontan tertawa. Ibu pemilik warung itu juga. Berikutnya Nasirun.
Sebuah lori besar bermuatan batu, lewat di depan kami. Suaranya menggelegar memecah dini. Memecah tawa kami. Menyisakan abu-abu debu di belakangnya.
Kami hirup, kami nikmati, sisa-sisa debu yang beterbangan itu. Berikutnya kami umpati! Tiba-tiba saya teringat pada selarik bait sajak si tua, WS Rendra*
…
kemiskinan yang mengekang
dan telah lama sia-sia cari kerja.
Ijasah sekolah tanpa guna.
Para kepala jawatan
akan membuka kesempatan
kalau kau membuka paha.
…
* Dari Kumpulan Sajak Blues untuk Bonnie; Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta.
Batam, 7/8/05