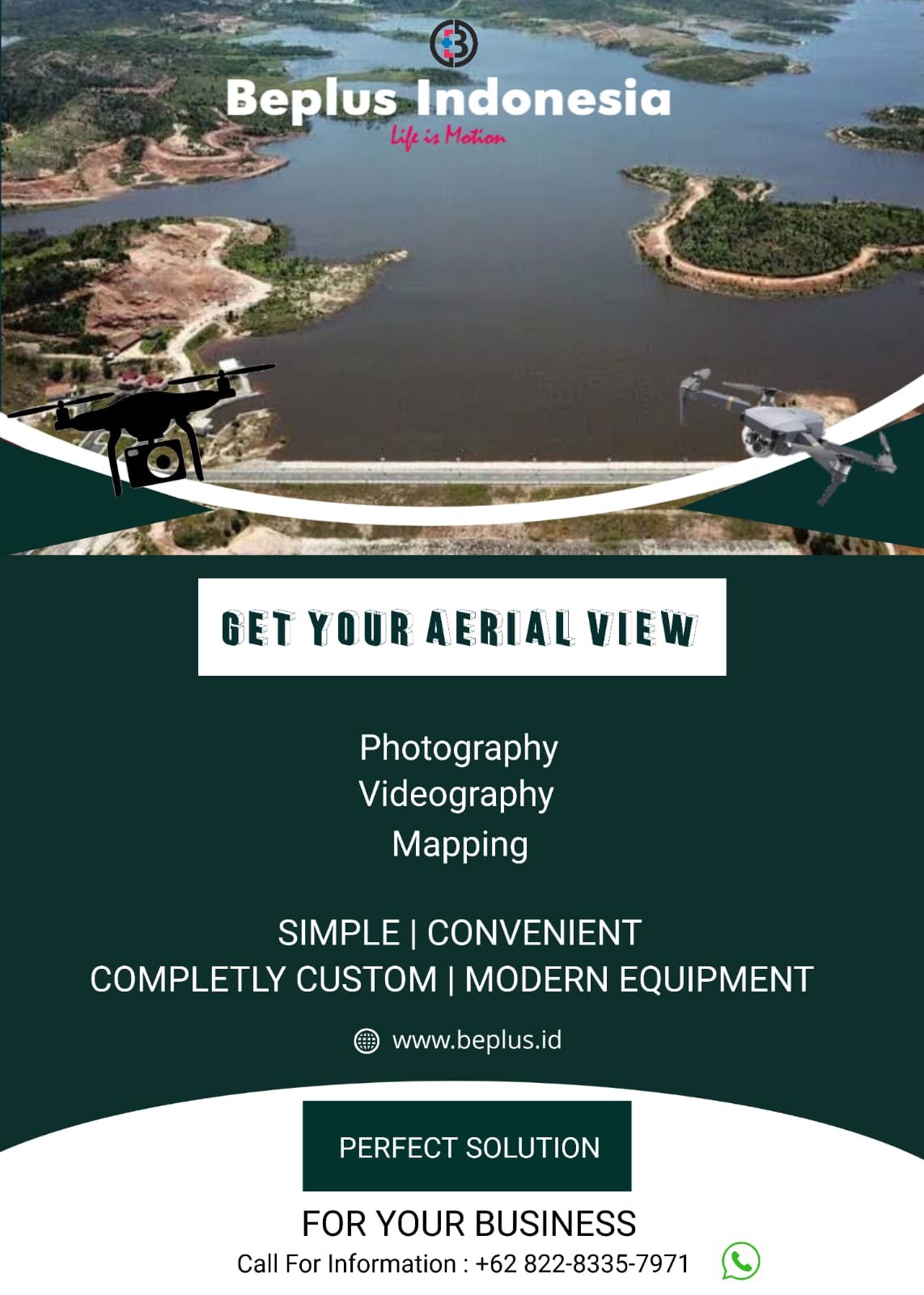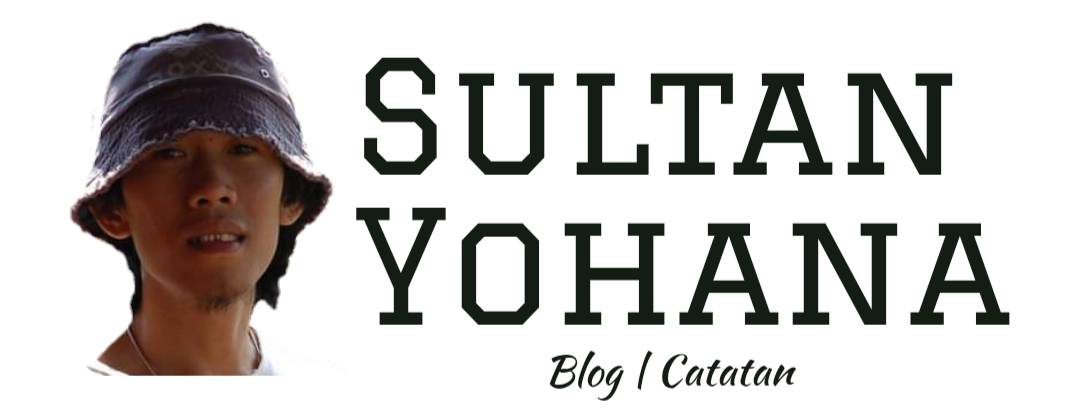Bahkan di Batam, persoalan tanah bisa merembet ke isu SARA.
Begitu keluar dari pintu gerbang sekolah dasar, Rabu (16/7) siang itu, anak sulung saya, Ken Danish, sudah ‘ngoceh’ soal kegiatan sekolah yang akan diikutinya esok hari. “Papa, esok ke sekolah harus pakai pakaian adat. Kami ada selebrasi Racial Harmony Day. Saya mau pakai pakaian China,” kata dia sambil berjalan setengah lari mengikuti saya yang memang tak bisa berjalan pelan. Hmmm, bukankah Racial Harmony Day, atau jika saya bahasa Indonesiakan secara bebas berarti Hari Anti-rasis atau Hari Keharmonisan Etnis di Singapura, jatuh pada Senin pekan depan? 21 Juli? Di sekolah playgroup adiknya saja, Zachary, sang guru menginformasikan pada saya acara anti-rasis digelar pada 21 Juli. Ah.., kok kenapa tiba-tiba saya mempersoalkan soal “kapannya” selebrasi dilakukan. Bukankah, seharusnya pilihan Ken untuk mengenakan busana China jauh lebih menggelitik hati.
“Bagaimana kalau esok pakai pakaian Jawa?” saya bertanya pada Ken.
“No. Saya China, dan harus pakai pakaian China.”
“Lho, bukankah kamu separuh Jawa?” tanya saya lagi.
“Tapi saya tak mau pakai pakaian Jawa. Saya mau China.”
“Tahun lalu kamu pakai Jawa. Keren. Semua orang suka kamu pakai pakaian Jawa,”
“Tapi kawan-kawan banyak yang pakai pakaian China.”
Pada akhirnya, sayalah yang harus mengalah dengan kengototan bocah yang baru bersekolah kelas satu sekolah dasar itu. Malam harinya, ibunya sudah menyiapkan seperangkat pakaian etnis China warna merah menyala. Saya sempat menunjukkan tiga pakaian adat lainnya yang beberapa waktu lalu saya beli saat pulang ke Malang: seperangkat pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkon, pakaian sakerah dari Madura, serta satu stel pakaian takwa yang mirip pakaian Melayu plus kopyahnya. Tapi, lagi-lagi Ken menolak memilihnya. Padahal, di daftar isian ketika mendaftarkan Ken masuk sekolah dasar dulu, saya dan istri sepakat mengisi kolom etnis: Javanese.
Tahun lalu ketika Ken masih belajar di taman kanak-kanak, di perayaan Racial Harmony Day 2013, kami memilihkan seperangkat pakaian Jawa untuk ia kenakan. Ketika itu dia senang, tak protes, serta semua orang di sekolahnya juga terkesan. Terkesan, terutama melihat blangkon coklat lurik yang Ken kenakan. Bahkan akhirnya, pihak sekolah meminta seperangkat pakaian yang dikenakan itu, untuk dijadikan koleksi sekolah. Kami menyumbangkan seperangkat pakaian itu, dan membeli dua perangkat lagi saat bulan Juni 2014 lalu saya pulang kampung ke Malang, Jawa Timur. Satu untuk Ken, satu lagi untuk Zachary yang belum genap berusia dua tahun.
Sebetulnya saya sama sekali tak mempersoalkan apakah dua anak saya kelak akan lebih condong ke Jawa (baca: Indonesia) ataupun China/Singapura. Jauh-jauh hari saya bersama istri sudah sepakat, kedua anak kami akan menjadi “milik dunia”, sebisa mungkin mengglobal untuk menghapus sekat-sekat bernegara yang selama ini membatasi pergerakan kami. Sekeluarga yang memang berlatar-belakang beda negara, keyakinan, dan kebudayaan. Sebelum tidur, saya sering berbicara penuh harap kepada Ken, kelak semisal dia jadi dokter, jangan cari uang dengan berpraktik di Singapura. Melainkan pergilah ke Indonesia, ke daerah paling pelosok, untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan dan tak mampu pergi ke dokter. Ken tentu saja belum terlalu mengerti apa yang saya bicarakan. Tapi saya yakin, di otaknya, bakal selalu terekam memori itu, dan semoga kelak jika harapan saya terkabul, memori itu bisa bangkit dari pikiran Ken.
Untuk terus menabung memori baik pada anak-anak kami, kami sekeluarga juga selalu mengagendakan pergi jalan-jalan ke daerah berbeda tiap tahunnya. Setiap daerah yang kami tuju, kami berusaha memilih daerah atau kota kecil yang di dalamnya kami bisa bergaul dan bertemu dengan masyarakat setempat. Belajar apa pun perbedaan yang mereka punya. Saya ingin menunjukkan pada anak-anak saya dengan bahasa yang “sederhana”, bahwa dunia ini begitu luas dengan orang-orang yang sangat berbeda. Bahwa dunia ini tidak hanya sebesar kotak i-Pad kesayangannya saja. Di rumah, kami juga mempraktikkan secara bersama-sama, antara Bahasa Inggris, Jawa, China, maupun Bahasa Indonesia – juga ayat-ayat Alquran dan doa bahasa Arab.
***
Saya selalu tertarik dengan setiap gerakan melawan rasisme. Singapura menjadi contoh keren bagaimana resisme ditempatkan sebagai “musuh” bersama yang harus dilawan sedini mungkin. Sebagai puncak dari perlawanan itu, saban tahun Singapura merayakan Racial Harmony Day, atau kalau saya bahasa Indonesiakan secara bebas bisa berarti Hari Anti-rasis atau Hari Keharmonisan Etnis. Bahkan sejak balita, sebagaimana anak saya Zachary yang usianya belum genap dua tahun, sudah terlibat di dalamnya. Sekolah-sekolah menggelar Racial Harmony Day. Distrik-distrik (baca: kecamatan) di Singapura juga menggelar acara serupa di mana-mana. Tahun 2014 ini, Racial Harmony Day mengambil tema “Harmony from the Heart”. Harmoni antar-etnis, dari tema yang saya baca di situs Kementrian Pendidikan Singapura, bisa terwujud jika hati bisa menghargai perbedaan sekecil apa pun dari masyarakatnya.
Sebagai kota-negara heterogen yang nyaris seluruh etnis di seantero dunia bisa ditemui di Singapura, Racial Harmony Day seperti segelas air putih di tengah tenggorokan dahaga di terik matahari yang panas. Ini jika kita melihat di Indonesia, bagaimana persoalan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), dijadikan “komoditi” oleh politikus-politikus tak punya hati yang yang merebut kekuasaan. Isu SARA dianggap para politikus kotor tersebut, sebagai bahan seksi untuk diprovokasi. Mereka tidak peduli, potensi kerusuhan, perang, pertumpahan darah, yang bisa terjadi karena isu SARA yang mereka mainkan. Di Batam misalnya, persoalan lahan saja, bisa merembet hingga ke persoalan kesukuan dan agama. Ini jelas sangat berbahaya. Pemerintah Indonesia, terutama politikusnya, seolah tidak serius menggarap pendidikan tentang rasisme dan menghormati setiap perbedaan, karena mereka menganggap, justru isu tersebut menguntungkan mereka. Mereka kerap “menjaring suara” masyarakat, dengan memunculkan isu-isu seputar SARA.
Di Singapura, perang terhadap rasisme secara terus menerus, seperti mengingatkan pada setiap orang, apa pun ras yang Anda miliki, apa pun agama yang Anda yakini, sehebat apa pun keluarga yang Anda miliki: semuanya setara di mata negara. Setara dalam hal kesempatan apa pun, untuk menjadi apa pun, untuk memilih cara hidup bagaimanapun. Di Singapura – yang saya rasakan – hanya ada dua model manusia yang bisa menentukan cerah tidaknya masa depan kelak. Yakni model manusia yang RAJIN, dan manusia PEMALAS.
Penghormatan pada perbedaan memang betul-betul terasa di Singapura. Bahkan Anda bisa dengan mudah menemuinya di jalan-jalan, di pasar-pasar, di bus-bus, maupun di kereta api atau mal-mal. Wanita-wanita etnis India, dengan pedenya masih berpakaian sari saat jalan-jalan di mal, atau pemeluk Budha yang dengan bebasnya menaruh sesaji di bawah pohon pinggir-pinggir jalan seantero Singapura. Saya juga gembira ketika melihat bocah-bocah seusai pulang dari masjid belajar mengaji, masih berkopyah sembari menenteng skate-board. Jika hari Minggu, cobalah datang ke daerah City Hall, di sana Anda akan bisa menyaksikan wanita-wanita muda dari Myanmar, banyak yang memakai selendang khas negara mereka sebagai rok. Tulisan-tulisan penunjuk arah, papan pengumuman di tempat umum, tak jarang ditulis dalam beberapa bahasa yang digunakan warga Singapura.
Sekitar 12 tahun silam, saat-saat pertama saya datang ke Singapura, mungkin sedikit susah kita menemukan sepasang kekasih berlainan etnis, berlenggak-lenggok mesra di tempat-tempat umum. Tapi kini, Anda akan mudah menemukan pemuda India, tengah mengandeng mesra tangan wanita China. Atau pria Melayu sedang mojok pacaran dengan bule Eropa. Dunia Singapura, dengan menepatkan rasisme sebagai musuh utama, kini seolah-olah menyatu hanya dalam satu kesamaan: semuanya adalah MANUSIA.
(sultan yohana)