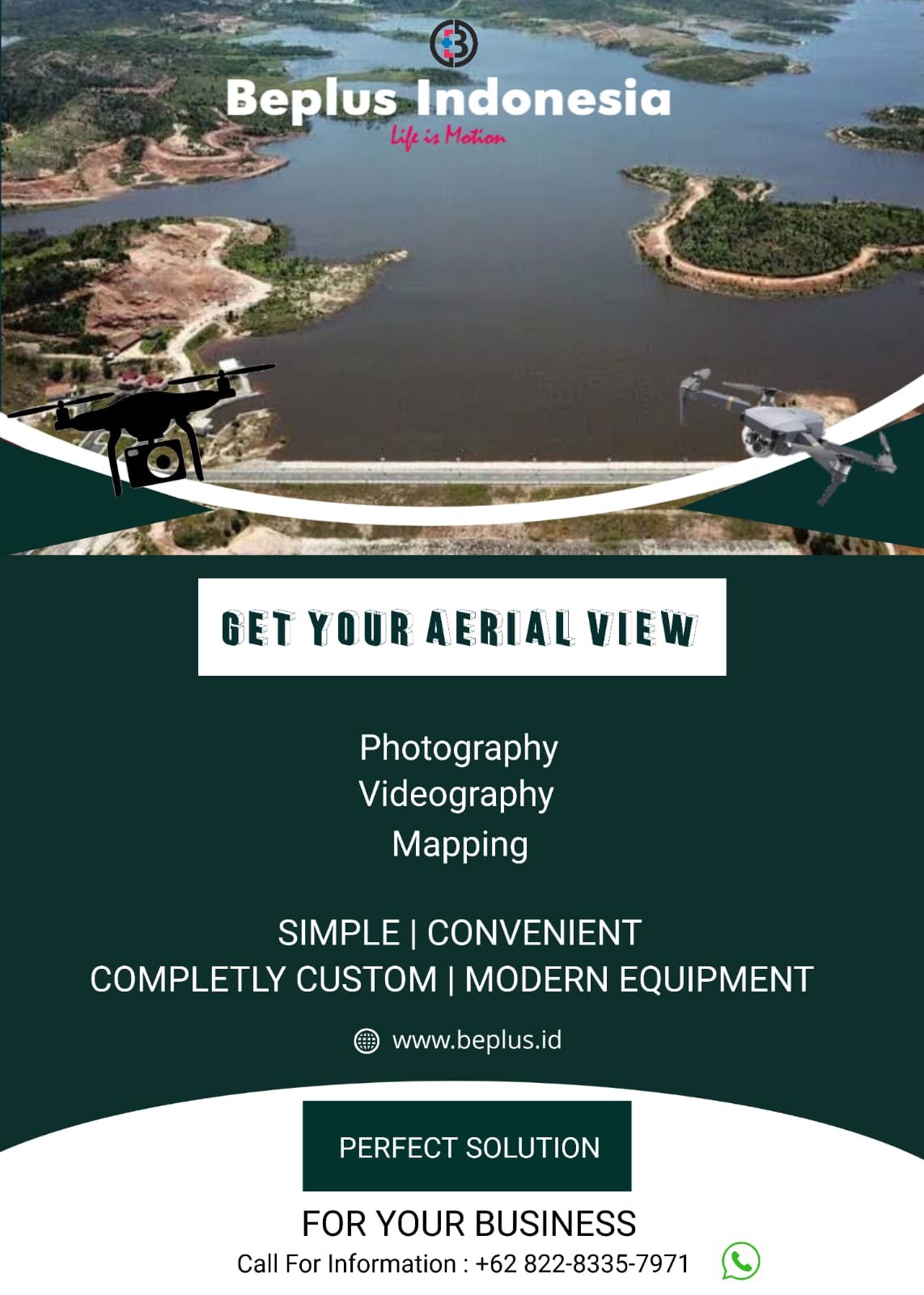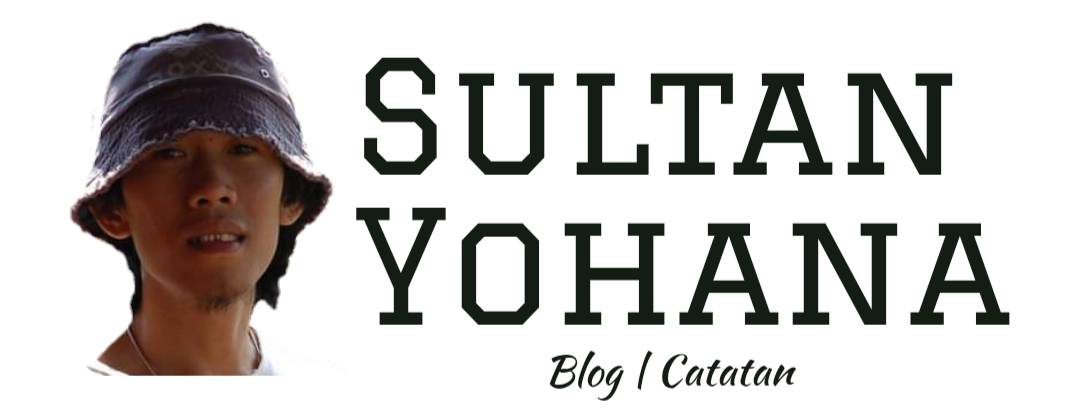Menjelajahi Batam pada malam hari, kini, seakan berjalan di antara nisan-nisan. Manusia-manusianya, lebih memilih merapat di pusat-pusat perapian: mal yang menjamur dan nyaris menenggelamkan Batam di dasar kekakuan. Yang tersisa di jalan-jalan hanyalah mata nyalang preman yang tengah mengincar mangsanya; pemabuk-pemabuk yang tak sadar di trotoar, bencong-bencong lapuk; dan pengojek yang duduk memojok di pangkalannya, sembari merapatkan jaket kumalnya. Menjelajahi Batam pada malam hari, tidak lagi menciptakan cerita-cerita menggembirakan.
Tepat di perempatan simpang Bea Cukai, Batuampar, tiga tahun silam, aku pernah jatuh hati pada seorang waria. Monica dia memperkenalkan diri. Kecantikannya luar biasa. Sempurna. Dan dia siap melakukan apa saja untuk menyenangkanku malam itu. Sayang, dia tidak berlubang! Dan ketika itu, aku benar-benar menginginkan sebuah lubang. Aku hanya jatuh hati padanya karena kesempurnaan kewanitaannya. Sayang, dia bukan sebenar-benarnya wanita.
Tapi di manakah Monica kini? Kenapa di sepanjang simpang ini, yang tersisa hanyalah waria-waria lapuk berpenyakit yang silikon penyangga hidungnya telah mencair menghadirkan kengerian surealis? Aku ingat ketika bertemu dan berkenalan dengan Monica. Ketika itu, kami – aku dan seorang rekanku lelakiku – tengah merayakan perpisahan, menjelajah Batam di gemerlap malam. Dengan keluwesan bahasa tubuh dan kata-katanya, Monica langsung membuat kami bergairah.
Teman lelakiku maju terlebih dahulu. Kepengecutannya mungkin sudah direngguk bergelas-gelas alkohol yang sebelumnya kami nikmati. Dia menggandeng Monica menuju surga. Aku mengantarkannya dengan pandangan mata menanar. “Kawan, akhirnya kau jadi lelaki sejati juga,” cekakakku dalam hati.
Dan cerita di tiga tahun silam itu berlanjut semakin menggembirakan. Tubuh rekanku muncul dari semak belukar. Dengan cekikik khas anak muda, kami langsung kabur, memacu motor dengan gila-gilaan. “Berapa rupiah kau selipkan di payudaranya?” tanyaku pada sang rekan. Dia tertawa lagi. “Cukuplah untuk membeli sepotong roti,” jawabnya.
Hanya sepotong roti? Diancok! Kau menghargai kecantikan Monica yang sempurna dengan rupiah yang hanya cukup untuk membeli sepotong roti? Keterlaluan! Dan aku tak sempat mengembangkan umpatanku ketika kawanku dengan kekasaran yang mengagetkan memintaku menghentikan laju motor. “Kita kembali ke Monica. HP-ku hilang,” kata rekanku resah.
Sekembalinya ke surga, Monica sudah tidak ada. Tentu saja. Dan kawanku, mengumpat tiada tandas ketika kuantar pulang. Ketika itu, Batam masih gemerlap. Salahmu sendiri, rekanku! Kau hargai kecantikan Monica dengan sepotong roti! Dan harga HP-mu, mungkin setimpal dengan kecantikan Monica, pikirku.
Tapi kini, ketika aku kembali menjelajah malam. Di jalan-jalan. Kegembiraan itu seolah menghilang. Yang terjejal, adalah debu-debu memekak mata yang dihasilkan truk-truk bertonase besar, menggilas jalan-jalan berlobang.
Tapi bagaimanapun, Batam tetap seksi. Seseksi Kate Winslet ketika beradu akting dengan Leonardo De Caprio di Titanic. Dan Batam, Titanic itu, kini perlahan-lahan mulai tenggelam. Terbeban oleh mal-mal raksasa, bukit-bukit yang ditebang, pantai-pantai yang diuruk, dan manusia-manusianya yang dipaksa menumpang di dalamnya.