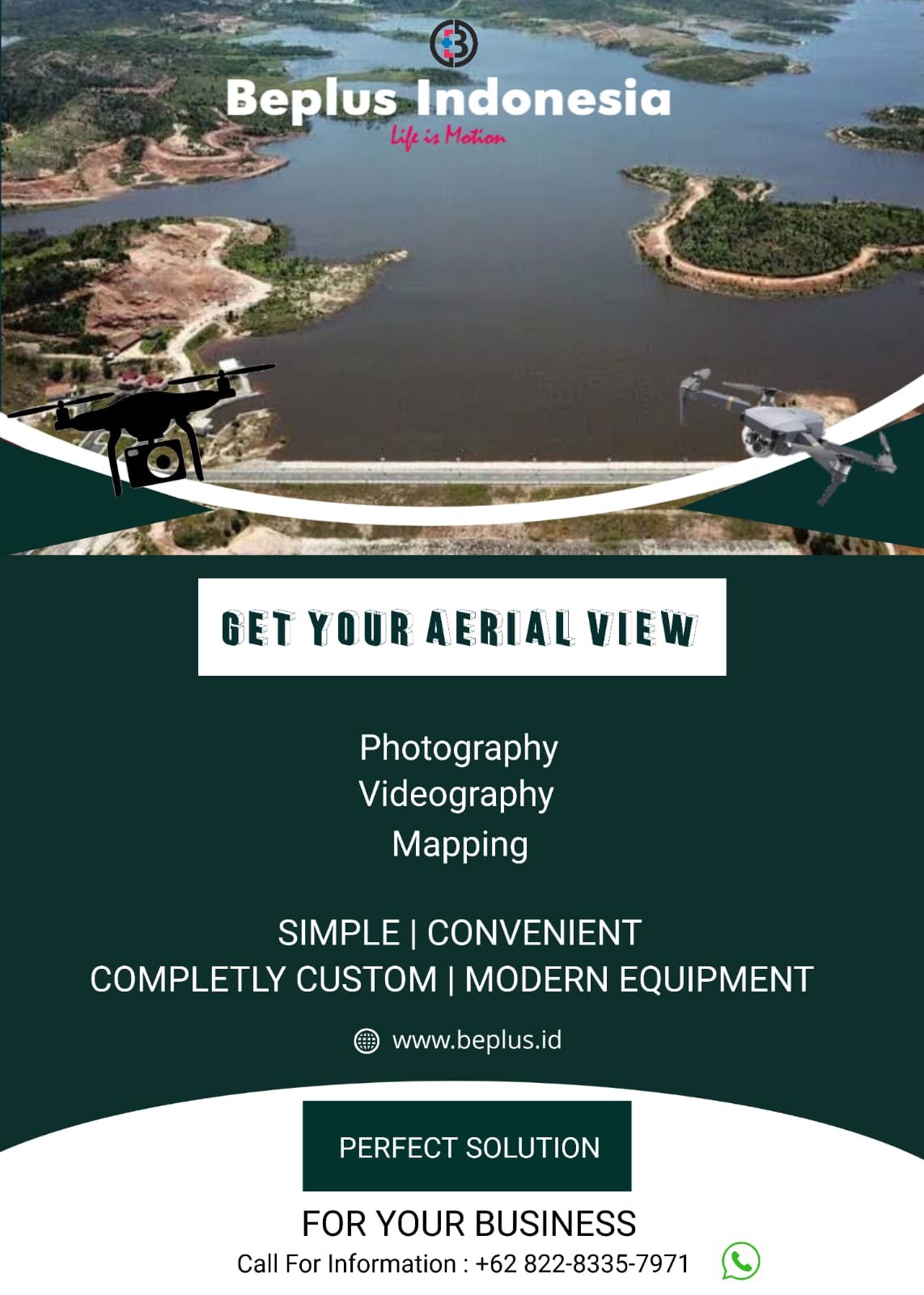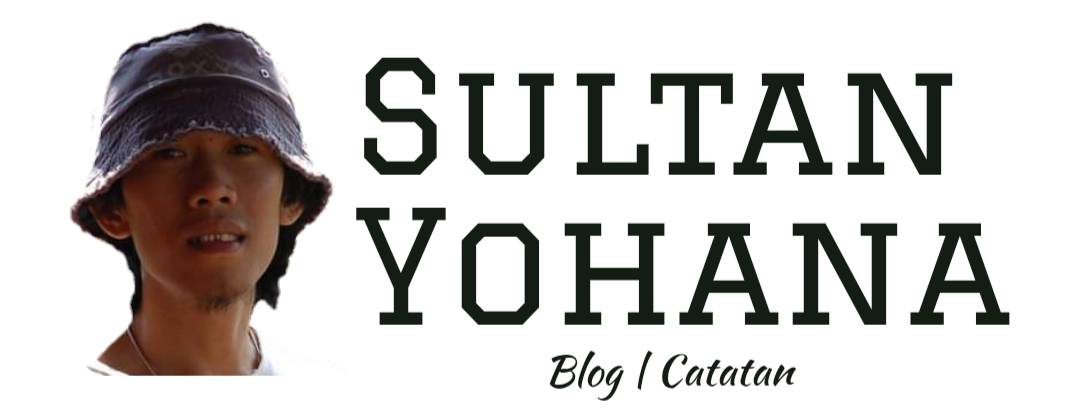: Akhir April yang Selalu Gundah
Dahulu kala, saat masih sekolah. Menjelang jelang akhir April, dan memuncak bulan Mei, adalah hari-hari paling meng-gundah-kan, sekaligus sedih bagi saya. Bahkan rasa sedih itu masih bisa saya rasakan hingga kini. Hari-hari, ketika saya sekolah dari madrasah hingga SMA, akan menghadapi ujian untuk kemudian rapotan. Gundah karena harus bayar ini-itu, tunggakan SPP, uang ujian, dls.
Ibu saya single parent (sejak saya berusia tujuh bulan), dengan dua anak. Belakangan setelah saya berusia 17 tahun, ibu menikah lagi, dan setahun kemudian lahir adik bungsu saya. Ibu punya usaha mracang, alias punya toko kelontong kecil di depan rumah. Semula, di awal-awal buka, tokonya lumayan besar, ramai, dan kami tak pernah kekurangan apa-apa. Ibu adalah orang pertama yang buka toko kelontong di dua RT tempat tinggal kami. Belakangan, setelah mengetahui sukses ibu, banyak tetangga ikut-ikutan. Dengan modal lebih besar, dan suami yang bekerja, para tetangga yang buka usaha serupa, kemudian “memakan” usaha ibu. Meski tidak benar-benar mati, usaha kelontong ibu bertahan antara hidup dan mati selama berpuluh tahun. Ibu juga kerap nyambi ngambil cucian dan setrikaan tetangga.
Selama itulah, dari hasil usaha ala kadarnya tersebut, saya dan kakak bisa bersekolah. Bahkan kakak saya, adalah orang pertama yang bisa lulus kuliah di lingkungan RT kami. Bukan karena tetangga yang lain tidak mampu, bahkan mereka jauh lebih kaya-kaya. Tapi kebanyakan di kampung saya ketika itu, sekolah tinggi, apalagi untuk seorang gadis, bukan menjadi prioritas utama. Keluarga kami sempat diece (diejek) oleh tetangga-tetangga, “ngapain menyekolahkan Irma (kakak saya) tinggi-tinggi, toh setelah itu kawin punya anak”.
Ada Pak Haji juragan besar tetangga saya, yang anak perempuan satu-satunya, bahkan sudah menikah setelah lulus SMP. Saya sendiri tidak tahu, dan tidak hendak bertanya, apa alasan ibu memprioritaskan sekolah pada kami berdua, anak-anaknya. Padahal dia hanya lulus madrasah saja, dan saat itu ekonomi keluarga kami benar-benar kelimpungan.
Karena usaha mracang pula, biasanya saya kebagian jaga warung, dan alhamdulillah secara tak sengaja saya berhobi membaca. Karena di rumah tidak ada tivi, radio, dan sebangsanya, untuk membunuh waktu, saban hari saya terpaksa “menguliti” koran/majalah bekas yang sedianya untuk bungkus dagangan. Kalau ingin bacaan lebih “mewah”, saya biasanya lari ke taman bacaan berbayar di dekat pasar, namanya “Garuda”. Perpustakaan sekolah? Nyaris semua buku yang bagus sudah saya pinjami.
Kadang kalau semua sudah habi saya baca, saya bingung cari bacaan lain, dan akhirnya buku-buku pelajaran milik kakak saya, terutama IPA dan sejarah, menjadi bacaan berikutnya. Mungkin karena itu, di madrasah, pelajaran IPA saya adalah yang terbaik, dan saya sempat bercita-cita jadi seorang ilmuwan, hehehe.
Tapi saya tidak besar di Singapura, yang perpustakaannya begitu mewah, serta bersekolah begitu mudahnya. Saban tahun, setiap akhir April, atau awal-awal Mei menjelang ujian, hati saya selalu gundah. Terpikir, bagaimana ibu saya bisa melunasi SPP yang menunggak sejak dari awal bulan tahun pelajaran pertama? Barang berharga apa lagi di rumah yang bisa digadaikan ibu, untuk membayar uang sekolah? Bayar uang ujian saya? Mengingat itu, saya benar-benar jadi membenci sekolah.
Sejak madrasah hingga SMA, saya memang tak pernah bisa membayar SPP saban bulan. SPP baru terbayar menjelang rapotan kenaikan kelas. Itu setelah ibu berikhtiar menggadaikan barang berharga apa saja di rumah. Barang-barang itu kemudian dicicil pembayarannya hingga setahun, dilunasi untuk kemudian dibawa pulang. Dan digadaikan lagi beberapa minggu kemudian ketika saya akan membayar uang sekolah. Begitu saban tahun, terus berulang hingga saya lulus SMA. Pegadaian, bagi saya, memberi manfaat yang begitu besar.
Jangan tanya peralatan sekolah seperti tas atau sepatu. Untuk saya, biasanya, saya mengandalkan peralatan bekas sepupu kaya saya di Karangploso, yang kebetulan usianya sepantaran dengan saya.
Beruntung saya tidak bodoh-bodoh amat. Saya selalu bisa sekolah di sekolah bagus dan murah di tempat tinggal saya, tanpa pernah ketinggalan kelas. Kakak saya, bahkan selalu berupaya mendapatkan beasiswa selama dia sekolah, bahkan hingga ia lulus kuliah. Hingga, beban ibu untuk menyekolahkan kami, tidak berat-berat amat.
Bulan April, bukan hanya mengingatkan saya akan Kartini karena posting rekan-rekan Facebook yang suka mengupload foto anak-anak mereka yang baru saja Kartinian. Setiap bulan April pula, saya selalu mengingat tentang kegundahan saya di masa silam. Mengingat sebenar-benarnya “kartini” saya, ya… ibu saya itu.
Ibu saya, Bu Zumronah namanya! Perempuan paling kuat yang pernah saya kenal di dunia ini.