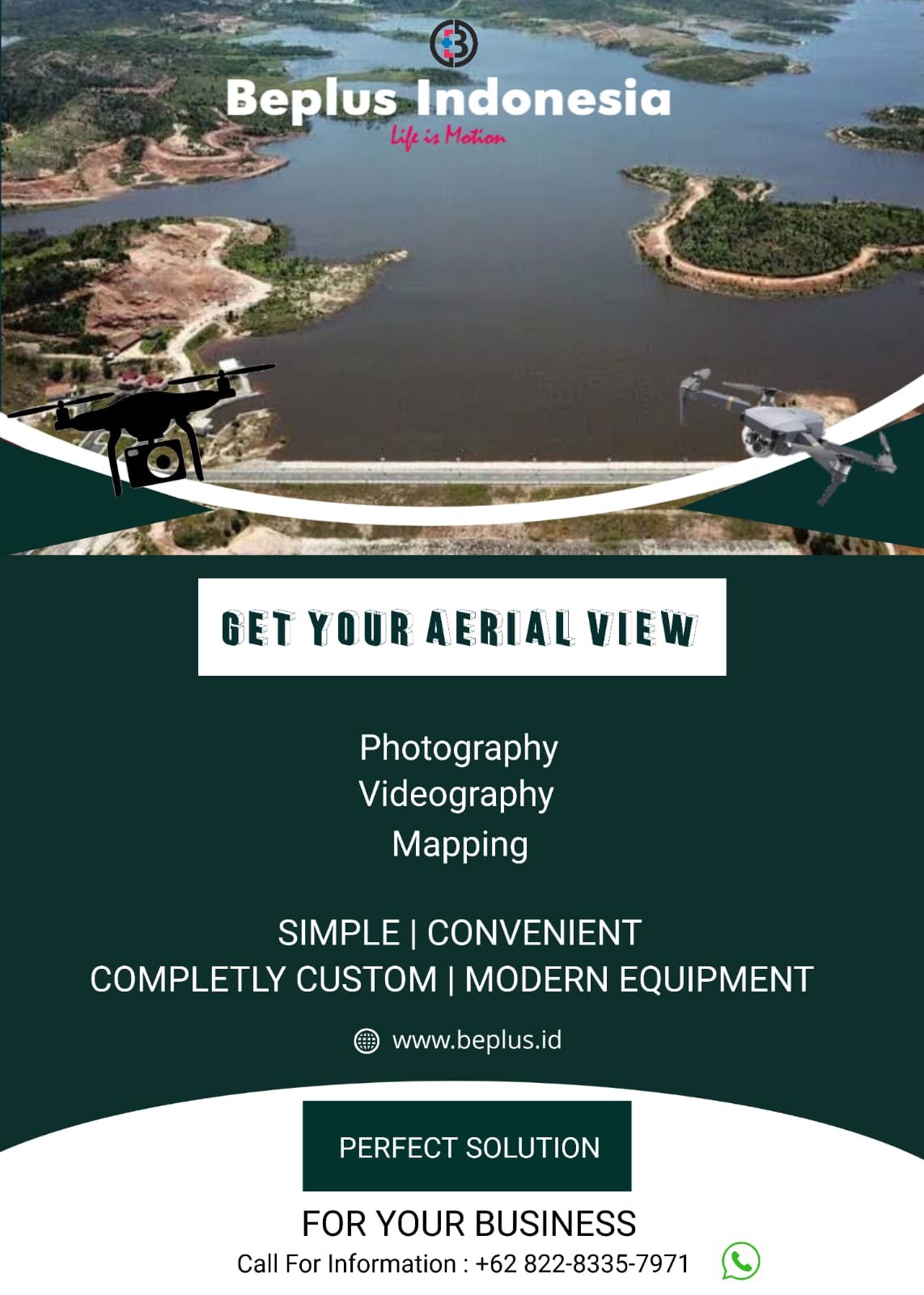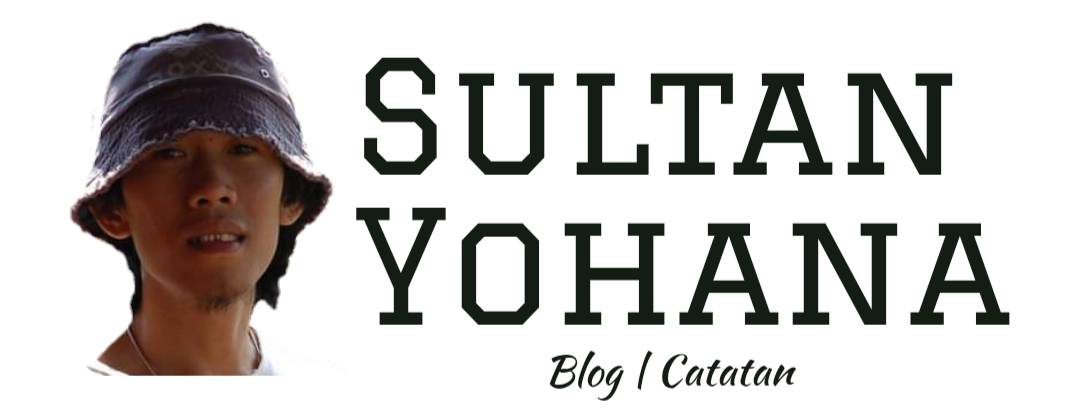Kami dipaksa berdiri cukup lama: menunggu ada satu meja yang kosong yang ditinggalkan pembeli yang selesai makan siang. Di foodcourt lantai dasar Bandara Internasional Changi, jarum jam pada hari Sabtu (10/12/2011) belum pas betul di waktu istirahat makan siang. Kami: saya, Joanne dan Ken, baru saja terbebas dari kebosanan 2,5 jam penerbangan Bali-Singapura dengan pesawat budget rendah, Value Air. Telinga ini masih berdenging-denging karena tekanan udara, dan otot-otot masih kaku oleh kursi sempit antarpesawat. Namun perut ini lebih kencang berbunyi, lapar minta diisi.
Sialnya, puluhan kursi duduk di foodcourt Bandara Changi sudah penuh. Saya sempat iri ketika melihat seorang pria paruh baya, terlihat asyik menguasai satu kursi sofa seorang diri sembari memainkan telepon pintarnya. Dalam hati, semoga ia melihat ke arah kami, kemudian iba melihat berat bawaan kami plus bocah empat tahun yang sudah mulai mengeluarkan rengekan, hingga kemudian merelakan kursi sofa yang ditempatinya untuk kami. Tapi itu tidak terjadi.
Pundak ini serasa akan copot karena membawa ransel besar, ketika pada akhirnya, sebuah keluarga meninggalkan meja seusai menyelesaikan makanan. Saya cepat-cepat berdiri di samping meja yang belum sepenuhnya dibersihkan tersebut agar tak keduluan pengunjung lain. Tas berisi pakaian kotor kami dari backpacking empat hari di Bali, langsing saya taruh di kursi. akhirnya, dapat juga tempat duduk untuk makan siang.
Padat pengunjung, tidak hanya mengurapi foodcourd lantai dasar Changi yang memang bisa diakses bebas siapa pun orang. Riuh pun terlihat di resto-resto cepat saji seperti McD, KFC, maupun tempat makanan favorit saya, Ya Kun Kaya Toast yang roti bakar dan kopi O-nya selalu menggoyang lidah saya. Semuanya penuh. Sebagaian kursi tempat makan dipenuhi oleh karyawan-karyawan yang memang bekerja di Changi. Tapi, sebagian lagi disesaki oleh pengunjung domestik yang menjadikan Changi sebagai tujuan wisata akhir pekan. Saya perhatikan, banyak sekeluarga kecil dengan pakaian ala kadarnya, t-shir,celana pendek dan sandal jepit; yang akhir pekan itu berkunjung memadati Changi.
Si Ken, yang sedari tadi jengkel karena riuhnya bandara, kemudian mengambil duduk di kursi lainnya. Mengeluarkan mainan dari tas ranselnya, sesaat kemudian dia sudah sibuk dengan mobil-mobilannya. Istri memesan makanan: sup ikan plus nasi seharga 4 dolar (sekitar Rp28 ribu), dan makanan Korea kegemarannya. Sementara otak saya, cuma bisa memaki suasana terlalu krowded yang saya dapati di hampir semua penjuru Changi. Suasana seperti ini, memang kerap membuat saya tersiksa.
Telinga ini masih saja mendengung-dengung.
Di ujung jalan tadi, Ken sempat merengek minta main di playground yang ada di tengah bandara. Ia juga ngamuk ketika kami larang masuk toko mainan yang ada di koridor karena perut kami sudah teramat kering. Sebetulnya, saya sempat tergoda melihat t-shirt di toko-toko sandang yang menjual dagangan dengan diskon jor-joran. Harga yang saya perkirakan, lebih murah ketimbang yang ditawarkan di mal-mal lain di Singapura. Tapi renge’an perut ternyata lebih keras terdengar.
Changi seperti mal saja. Bahkan nyaris sama dengan mal-mal di daerah paling beken di Singapura, Orchard Road. Perputaran ekonomi di sini, tak hanya sekedar berhubungan dengan lalu-lintas penumpang pesawat atau layanan pesawat itu sendiri. Changi sudah seperti magnet ekonomi yang menawarkan hampir semua kebutuhan warga Singapura. Dari mulai sekedar roti bakar nyam-nyam yang ditawarkan Ya Kun Kaya Toast, hingga tas Hermes yang digemari Nunun Nurbaetie, buronan “lupa ingatan” yang baru ditangkap KPK di Bangkok itu. Belanja di Changi, kita tak terasa “dicekik” oleh harga yang tinggi.
Semua harga barang dagangan normal. Bahkan beberapa di antaranya lebih murah karena bebas pajak. Saya pernah membeli tas kamera di dalam Bandara Changi, lebih murah sekitar 20 dolar ketimbang harga di luar bandara.
Changi juga sudah seperti ruang publik sekaligus kawasan wisata – yang sebagiannya bisa dinikmati secara gratis – yang bisa dijadikan alternatif warga lokal untuk berakhir pekan. Mengajak keluarga mereka jalan-jalan ke sana. Bahkan pengelola di sana, menyediakan sarana pelajaran gratis seperti arena menggambar bagi anak-anak. Itulah kenapa, Changi menjadi salah satu tujuan darmawista pelajar taman kanak-kanan dan SD di Singapura.
Saya beberapa kali mengajak Ken jalan ke sana untuk sekedar membeli mainan atau makan siang. saya memilih di sana, salah satunya karena cukup dekat dengan tempat tinggal kami di Singapura. Dari tempat tinggal kami di Hougang ke Changi, hanya butuh 15 dolar naik taksi, atau sekitar 1 dolar per orang jika naik bus kota.
Inilah yang berbeda dengan bandara-bandara di Indonesia. Sebelum kami naik pesawat, di Bandara Ngurah Rai, kami terpaksa membeli satu set pakaian Ken dengan harga dua kali lipat dari harga pasaran. Dalam hati saya menggerutu, kenapa kami bisa lupa membeli pakaian Ken di pasar rakyat. Apalagi kualitas dan bahannya sama. Sepanjang koridor di dalam Ngurah Rai, toko-toko yang berdagang apa saja nyaris sepi dilongok pengunjung.
Di Bandara Hang Nadim sama saja. Saya dulu sering nongkrong di sini, karena saya pernah tinggal di Perumahan Rajawali. Sebuah toko roti dengan pelayannya yang masih muda, kerap menjadi tempat saya nongkrong. Di awal-awal saya ke sana, saya selalu mengeryitkan dahi ketika harus membayar sangat mahal sepotong roti dan secangkir kopi. Mahal banget. Namun harga itu lama-lama kemudian berubah menjadi biasa, ketika ia tahu bahwa saya tinggal di Rajawali dan kerap nongkrong di kedainya.
Harga “mencekik” yang dipasang para pedagang di bandara Indonesia, justru memberi trauma tersendiri bagi para calon penumpang pesawat yang ingin membeli. Bahkan orang berduit sekalipun, rasa-rasanya enggan mengeluarkan uang dua kali lipat untuk secangkir kopi yang bisa dibeli dengan harga biasa. Ujung-ujungnya, ekonomi pun berjalan seret, dan pemasukan bandara juga tidak maksimal. Jika sudah demikian, bagaimana ekonomi bisa berjalan baik?
Singapura, dengan Changi Airportnya, memberi pelajaran bagi pengelola bandara di Indonesia.
(sultan yohana)