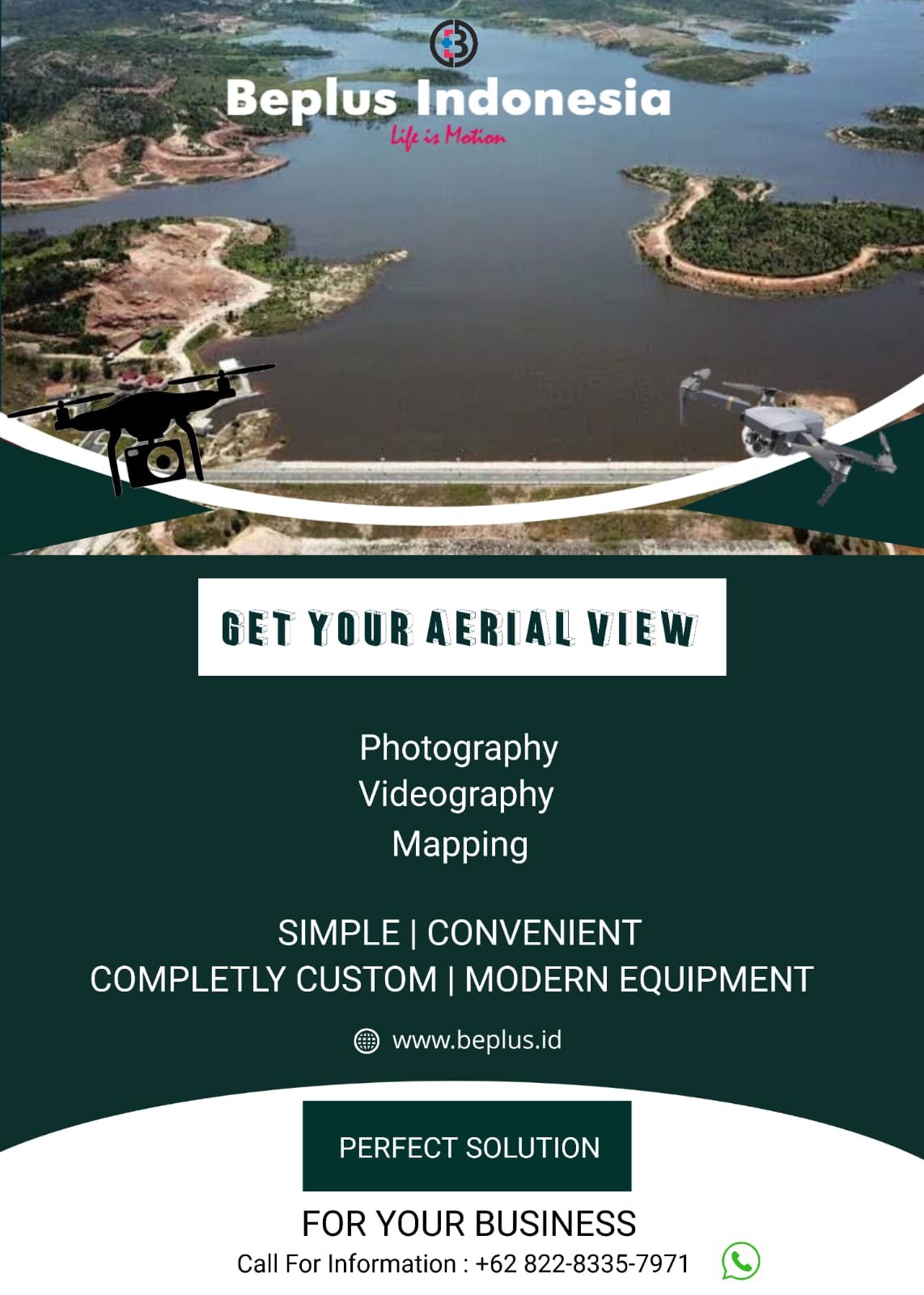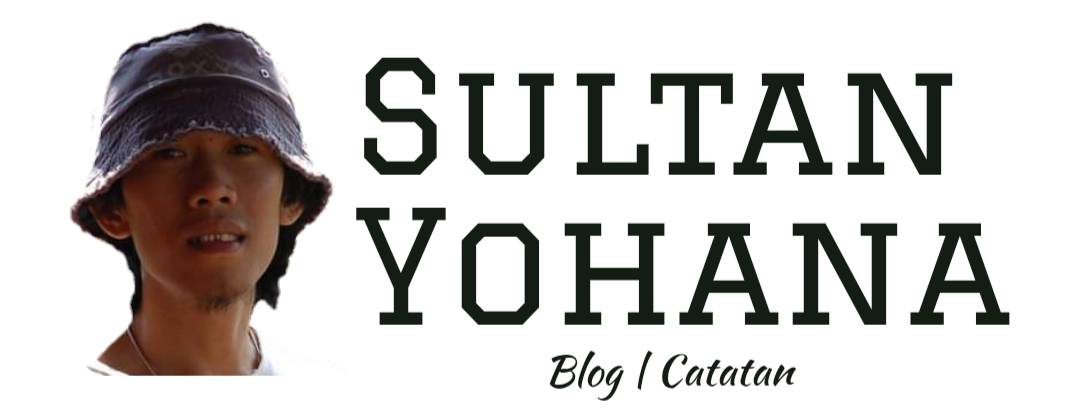Awal-awal mengajar di SMP Nurul Jadid, Bengkong, murid-murid pada protes ke saya. ”Kok, pakai kata “aku”, Pak! Kan, tidak sopan…,” ini bunyi sebuah protes. Satu kali, ketika saya kembali lupa, dan menyebut saya sebagai “aku”, protes kembali berterbangan.
Akhirnya, setiap kali saya hendak menggunakan kata ganti orang pertama dalam menyampaikan pelajaran, saya berhenti untuk berpikir sejenak. Hmm…, kali ini harus pakai “aku” atau “saya”? Alhasil, tersendatlah komunikasi dengan murid-murid. Tak jarang lidah ini kepleset hingga menyebut “aku”. Sering pula, memanggil diri “saya”, hingga terasa kayak gimana, gitu.
Nah, yang ini soal “saya”. Terbiasa memakai “saya” di depan kelas, di luar kelas masalah serupa muncul. Di YM, kata “saya” terbawa-bawa hingga kawan chatting saya dibuat merajuk. ”Mas ini apaan sih, sama saya kok bilang saya… saya… terus! Nggak matching!” ini protes Sari, kawan chatting dari Jakarta sana yang saat ini kebetulan lagi minta tolong bantuin nulis skripsi. Sari, yang protes itu, jelek-jelek (emang jelek sih) tiap hari ketemu Presiden SBY, lho! Lha wong memang kerjaannya ngepel lantainya Istana Negara! Becanda, Sar, he-he.
“Aku” kagak sopan. “Saya”, nggak matching. Trus harus bilang apa? Terus terang, untuk membiasakan diri memakai keduanya secara bersamaan, teramat sulit. Alhasil, saya sering mengatakan yang salah di tempat yang salah. Bilang “saya” di chatting, ngomong “aku” di depan kelas. Diamput!
Mau pakai “gw”, dikira sok gaul. ”Orang Batam aja, pakek kata anak Jakarte! Ape loo..,” mungkin begini gerundelan kawan-kawan sekantor. Kalau sudah begini, bisa tambah berabe.
Terbukti, kan, kata ganti yang sepele ini bisa menimbulkan masalah besar!
Berbicara soal ganti-mengganti kata, mata saya terasa “tidak nyaman” ketika membaca catatan lepas Pemimpin Redaksi Batam Pos Candra Ibrahim, berjudul Diskusi Konsul AS (Batam Pos edisi 2 Desember), Bagaimana bisa nyaman, ketika mendapati kata “saya” belepotan di mana-nama. Saya yang ini, jelas-jelas tidak nyaman untuk sebuah tulisan.
Saya petikkan paragraf pertama:
Siang kemarin, saya dikunjungi Konsul Amerika Serikat di Medan, Sean B Stein. Jauh dari kesan formal, pria yang pernah lama di Timor Timur (Timor Leste) dan Jawa itu, sendirian saja ke kantor saya, Garaha Pena, Lantai 2, Batam Center. Penampilannya bersahaja, mengenakan pakaian kasual dan celana dengan bahan dasar jeans (jins), memuji-muji Batam Pos sebagai koran yang paling modern di (se) Sumatera. Tentu saja saya tersanjung, meskipun saya tahu itu hanya bagian dari basa-basi, he..he….
Lihat kalimat pertama: Siang kemarin, saya dikunjungi Konsul Amerika Serikat di Medan, Sean B Stein. Kata “saya” itulah yang saya anggap tidak nyaman. Kalau si konsul Abang Sam yang datang ke Batam Pos untuk mengunjungi “saya”, jelas yang dibicarakan berikutnya adalah “saya”. Tentu pujian si konsul tertuju kepada “saya”. Bisa jadi bunyi pujiannya begini, ”Wah, makin keren aja si Candra ini…” atau, “Lama tak ketemu, kau kini tambah tembem.” Bahkan bisa begini, ”Udah nambah istri belum? Biar bisa nyaingi AA Gym.”
Tapi yang tertulis di kalimat berikutnya tidak demikian. Si konsul memuji-muji Batam Pos. Memuji-muji Batam Pos yang kata Pak Candra dengan bangganya, menjadi referensi utama Pak Konsul mencari informasi soal kawasan perdagangan bebas. Tak ada satupun kalimat yang memuji “saya”.
Candra = Batam Pos? Jelas tidak. Di sana ada sekian ratus orang yang bekerja. Ada reporter, ada redaktur, pimpinan umum, tukang iklan, tukang cetak, tukang sapu, tukang pemasaran, dls. Kalau saya jadi orang Batam Pos, saya pasti akan melayangkan protes pada Pak Chandra. Sedikit saran, alangkah elegannya, jika “saya”-nya Candra diganti “kami”. Bukan begitu, Pak Can?